Sudah lupa kapan terakhir membuat review tahunan album hip hop favorit saya, mungkin setelah Flip Da Skrip dirilis 7 tahun lalu dan memindahkan cara saya memandang arsip pribadi dan proses menulis. Setelah itu, saya tidak lagi merasa perlu menuliskannya setiap tahun. Entah karena energi dan waktu yang tak lagi sama, atau karena jarang ada sesuatu yang benar-benar menuntut saya duduk dan menuliskannya.
Tahun ini sedikit berbeda. Bukan karena saya tiba-tiba punya tenaga dan waktu berlebih, melainkan karena 2025 memiliki catatan khusus yang terasa penting secara pribadi. Sepanjang tahun ini hip hop semakin terlihat tidak lagi ambisius mencari bentuk baru (terlebih ketika bentuk baru itu memicu perdebatan dalam perkara teknis, misalnya; apakah ngerap 8 bar diulang-ulang termasuk ke dalam ‘bentuk baru’ atau dekadensi?) Alih-alih, 2025 menegaskan bentuk-bentuk yang masih bekerja; bukan sekadar bertahan, tetapi tetap menjadi bahasa yang memadai untuk berbicara tentang pengalaman. Banyak ragam pengalaman.
Jika satu dekade terakhir digerakkan oleh eksperimen teknologis, estetika trap, dan algoritmisasi distribusi, maka tahun ini terasa seperti ada jeda panjang yang bukan bentuk ‘pelestarian’ atau nostalgia kosong, tetapi pembacaan ulang terhadap kedalaman yang sudah ada. Saya menganggap hip hop di tahun ini tak lagi mengejar kejutan sonik semata namun pula sebuah rentang tahun konsolidasi.
Album-album terbaiknya menunjukkan bahwa genre ini tidak menua dengan nostalgia, tetapi dengan kesadaran, menjadikan waktu sebagai bahan, tidak lagi sebagai beban. Menyaksikan para legenda dari era masa muda kembali dengan bahasa yang masih memadai untuk berbicara tentang waktu, usia, dan sejarah. Veteran-veteran kembali bukan untuk mengulang kejayaan, tetapi untuk menguji ulang nilai dari kata-kata dan musik. Menguji ulang apa yang bertahan, apa yang benar-benar hilang, dan apa yang hanya berubah permukaannya. Mereka memperlihatkan hip hop sebagai seni penuaan yang aktif, tidak lagi untuk membuktikan “old heads menolak mati”, tetapi sebagai generasi yang kebetulan datang duluan, dan menunjukkan bahwa rap dapat menua tanpa kehilangan kehadiran. (saya bisa bicara lebih banyak soal ini terutama bicara soal proyek-proyek Spit Slam Records di lain waktu.)
Sedangkan generasi yang lebih muda memetakan eksplorasi, ingatan dan pengalaman baru sebagai cara untuk eksis dan bertahan, memperluas kosmos naratif melalui jazz-rap, avant-rap, dan dokumentasi intim kehidupan sehari-hari. Jika dekade sebelumnya adalah periode algoritma, 2025 menjadi interupsi (saya tidak tahu apakah sementara atau permanen) tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa arsip adalah masa depan yang bekerja sekarang.
Tak bisa dipungkiri, proyek kuratorial Legend Has It… yang diinisiasi label milik Nas, Mass Appeal, memainkan peran besar menjadikan 2025 begitu menarik. Proyek ini tidak hanya mengembalikan suara-suara klasik ke percakapan arus utama, tetapi juga secara tidak langsung membuka ruang bagi generasi tengah dan bawah tanah untuk menggali arsip personal, trauma, dan ritme keseharian sebagai bahan bentuk baru. Di luar proyek tersebut, bertebaran album lain dengan semangat serupa. Clipse dan De La Soul berbicara tentang kedukaan dan rantai keluarga tanpa sentimentalisme. Killah Priest memampatkan metode naratifnya. Nas dan DJ Premier memilih produksi minimalis sebagai ruang pengalaman dan kesaksian. Sementara billy woods (dan Armand Hammer), McKinley Dixon, hingga Saba membangun peta batin yang baru, membuat album yang tidak hanya didengar namun juga dihuni. Di tempat lain, produser seperti Apollo Brown, Lord Finesse, dan The Expert menunjukkan bahwa ritme tetap menyimpan ingatan bahkan ketika kata-kata absen.
Saya merasakan kembali ketegangan lama yang sama pada album-album yang saya temukan dan simak di tahun super brengsek ini. Menemukan kembali hip hop sebagai kerja mengingat, menahan dan mendorong, tidak selalu mendobrak. Jika era sebelumnya didorong oleh daya progress maju tanpa henti, maka 2025 seolah menata ulang garis waktu sedemikian rupa seolah Hip hop tidak lagi menuntut jawaban cepat.
Album-album berikut ini bagi saya pribadi bukan sekadar katalog musik tambahan, mereka menjadi arsip cara-cara baru untuk tetap hidup dalam suara, bahkan ketika dunia meminta kita berlari lebih cepat daripada diksi-diksi ‘pembangunan’. Sebetulnya, jumlahnya lebih dari yang saya tulis, namun saya harus membatasi. Nampaknya 22 album ini cukup mewakili. Saya susun bukan berdasarkan alasan urutan tertentu.
Awalnya saya ingin membuat ini menjadi semacam zine dengan layout yang sesuai sekaligus mencoba typeface set baru buatan sendiri. Tapi tahun baru tinggal beberapa hari lagi dan saya baru akan beranjak meninggalkan Maluku Utara menuju Bandung. So fuck it, mungkin lain kali.
Pantai Falajawa, Ternate, Des 2025
Slick Rick – Victory
Sejak Children’s Story dan The Great Adventures of Slick Rick menjadikannya raja dongeng jalanan pada 1988, nama Slick Rick selalu dikaitkan dengan fondasi storytelling hip hop: flow yang mengalir seperti dialog panggung, karakter vokal yang teatrikal, dan kemampuan menyusun adegan dalam bar seperti novel mini. Hampir semua MC naratif generasi berikutnya (dari Nas hingga Snoop Dogg, dari Ghostface hingga Kendrick) pernah menunjuk Rick sebagai inspirator dan rujukan standar teknis. Maka ketika Victory tiba pada 13 Juni 2025 sebagai album solo penuh pertamanya sejak The Art of Storytelling (1999), konteksnya bukan sekadar “comeback,” tetapi penegasan apakah legenda yang membentuk peta awal hip hop masih dapat berbicara dalam bahasa zaman sekarang.
Dirilis sebagai pembuka seri Legend Has It… dari Mass Appeal, Victory dikembangkan selama empat tahun proses kreatif lintas benua antara London dan Prancis, dengan Rick dan Idris Elba sebagai co-executive producer. Hasilnya adalah album berdurasi ringkas; 15 lagu, ±27 menit yang lebih tepat dibaca sebagai jurnal musikal ketimbang manifesto grandios: rap singkat, ide padat, humor licin, dan alur cerita yang menangkap fragmen perjalanan Rick di usia 60 tahun. Ya, Rick sudah setua itu hari ini.
Secara musikal, Victory kembali ke estetika yang Rick pahami sebagai dialeknya: boombap klasik, soul, dan reggae, semuanya diikat oleh gaya storytelling yang ringan namun berkarakter. Yang harus dicatat sebagai ironi, album ini juga mengikutsertakan trend musik aneh di akhir 80-an; hip-house yang dahulu dianggap sebagai gimmick marketing yang diwajibkan oleh tiap label rekaman pada roster-rosternya (EPMD sekalipun pernah jadi korban gimmick ini).
Di “Documents” bersama Nas, ia terdengar seperti menyambung tradisi Queensbridge yang dulu ia pengaruhi; sementara di “Stress” bersama Giggs, Rick menavigasi beat modern dengan kepercayaan diri seorang veteran, tidak memaksa terdengar muda, namun tidak terdengar usang. “Spirit to Cry” dan “Reflections on Brick Lane” mengungkap sisi kontemplatif yang jarang muncul eksplisit di era klasiknya, di mana rentetan memori, kehilangan, dan sedikit kegetiran hidup hadir tanpa melodrama.
Saya menikmati album ini terutama mengingat sekian lama ia absen, namun saya rasa lagu-lagu yang ia hasilkan terlalu ringkas untuk membangun kedalaman emosional, mereka lebih mirip momen-momen polaroid daripada potret besar yang lebih serius. Beat-nya solid, kolaborasi tepat sasaran, tetapi durasi pendek sering membuat lagunya seolah hilang sebelum sempat bertumbuh.
Saya berpikir mungkin Victory dibuat bukan untuk proyek pembuktian, hanya sebagai catatan kaki panjang dari seorang ikon yang tidak perlu mengejar tren untuk terdengar relevan (apa yang relevan dari trend hip-house?). Tapi paling tidak, album ini berperan sebagai jembatan antara dua generasi, mengingatkan bahwa storytelling, suara yang khas, dan karakter vokal tetap menjadi mata uang yang bertahan meski estetika hip hop berputar ke arah produksi digital, rap dimutilasi dan autotune menjadi backbone.
Lord Finesse – The SP 1200 Project: Sounds & Frequencies in Technicolor
Warisan Lord Finesse dalam hip hop dimulai dari perannya sebagai arsitek suara New York era 90-an: MC dengan diksi presisi dan punchline cerdas, produser dengan telinga tajam, dan anggota kunci DITC, sebuah kolektif yang mewariskan standar tertinggi untuk crate-digging, teknik sampling, dan estetika boombap. Di balik karya-karya Big L, O.C., dan Fat Joe, terdengar jejak produksinya: drum yang menampar, potongan soul yang dipahat presisi, dan swing khas SP-1200 yang menjadi fondasi bagi era yang menghubungkan block party Bronx dengan universitas studi hip hop hari ini. Dengan The SP 1200 Project: Sounds & Frequencies in Technicolor yang dirilis Maret lalu, Finesse tidak sekadar kembali. Ia mengingatkan mengapa beatmaking adalah bentuk arsip budaya sekaligus disiplin estetik.
Album berdurasi sekitar 55 menit dengan 17 trek instrumental ini merupakan surat cinta kepada mesin sampler legendaris SP-1200, perangkat yang membentuk suara rap jalanan sebelum digital workstation mengambil alih produksi. Alih-alih merayakan nostalgia mentah, Finesse memanfaatkan karakter SP-1200 untuk memperluas ruang sonik: neck-snapping drums, grit yang tidak disaring, serta lapisan sampel yang terasa “hidup” dalam ruang akustik lebih lega dibanding kompresi modern yang serba rapat. Pendekatan ini menghadirkan proyek instrumental yang bukan sekadar kumpulan beat, tetapi environment di mana drum, bassline, dan potongan suara menjadi narator tanpa vokal.
Trek seperti “Lo-Fi Cinema”, “The Gang’s All Here”, dan “King of Diggin’” menyalurkan energi boombap klasik secara langsung, live and direct. Swing yang tidak simetris, bass yang meresap, dan loop soul-funk yang bergulir seperti ingatan kota beton yang keras kepala. Sementara “Symphonic Collective” memperluas palet dengan sentuhan orkestral, membuat album bergerak dari potongan yang kasar ke lanskap yang lebih sinematik. Jarang ada beatmaker yang mampu sesinematik ini dengan SP 1200, sedemikian rupa sehingga mengalir tanpa MC namun tetap membangun naratif emosional.
Ide Technicolor dalam judul pula bukan gimmick. Finesse memperlakukan produksi sebagai permainan spektrum frekuensi. Setiap trek terasa seperti scene berwarna penuh, di mana tekstur sampel dan ruang drum memberi kesan kedalaman visual dalam format audio. Tidak mengherankan jika album ini juga berfungsi sebagai dokumen sejarah kecil. Beberapa beat merupakan rework materi yang pernah ditujukan bagi Big L atau Grand Puba, sehingga album terasa seperti arsip hip hop yang dibuka kembali dan diberi cahaya baru.
Saya memang rindu Lord Finesse hadir kembali sebagai MC, namun album instrumentalnya ini berbicara lain dan perlu dicatat. Paling tidak, bagi mereka yang menghargai beat sebagai pusat ekspresi, bukan sekadar penopang vokal, album ini menegaskan posisi beatmaking sebagai bahasa tersendiri dalam hip hop. Dalam lanskap rilisan 2025 yang dipenuhi proyek vokal dan kolaborasi besar, The SP 1200 Project berdiri sebagai pengingat bahwa hip hop tidak hanya hidup dari apa yang diucapkan, tetapi juga dari apa yang diambil, dipotong, dan dipertahankan dalam frekuensi. Ingat bagaimana lanskap hip hop berubah ketika DJ Shadow merilis Endtroducing?
Clipse – Let God Sort Em Out
Kembalinya Clipse setelah enam belas tahun tidak hadir sebagai nostalgia yang dibungkus produksi mewah, tetapi sebagai ujian ulang terhadap craft rap itu sendiri. Sejak Lord Willin’ (2002) dan Hell Hath No Fury (2006), duo bersaudara Gene “Malice” dan Terrence “Pusha T” Thornton telah membentuk mitologi jalanan yang tidak hanya mengandalkan keriuhan citra, tetapi juga ketelitian lirik, teknik rap dan etika internal. Hiatus mereka cukup panjang; Malice menuju perjalanan spiritual, Pusha T membangun karier solonya. Mereka meninggalkan ruang kosong yang tidak pernah benar-benar diisi siapa pun. Maka, ketika Let God Sort Em Out dirilis pada Juli 2025 dengan Pharrell Williams sebagai produser tunggal, pertanyaannya sederhana namun tajam: bisakah Clipse tetap relevan tanpa meniru versi terbaik diri mereka sendiri?
Jawaban pertama datang dari pembuka “The Birds Don’t Sing”. Trek ini tidak sekadar gelap, memiliki kemuraman yang intens; piano dan koor gospel menjadi fondasi bagi duka atas kematian kedua orang tua mereka. Jika ada ketidaksempurnaan dalam chorus yang sedikit pop, saya anggap bukan kelemahan, tetapi tanda bahwa Clipse tidak bersembunyi di balik formula lama. Mereka mengizinkan sesuatu yang rapuh menyelinap menjadi bagian dari sumber pengalaman.
Begitu album bergerak, Clipse segera kembali pada wilayah yang membuat mereka Istimewa; kepresisian lirik multisilabel yang bertemu produksi minimalis penuh ruang (well…, lengkap dengan analogi kokainnya tentu saja). “So Be It”, track favorit saya, adalah contoh sempurnanya. Pusha T tetap hadir serupa bilah yang terasah oleh kontrol, sementara Malice kini menulis dengan ketenangan yang justru mematikan. Anehnya, dinamika mereka tidak lagi terasa antagonistik, tetapi dialektis. Terdengar seperti dua perspektif yang tersisa dari dunia yang sama, namun tidak lagi dipandang dari jarak yang identik. Dalam hal ini saya harus memberikan applause bagi Malice yang tak lagi terdengar seperti sidekick.
Pharrell, sebagai produser tunggal, (yang kini punya catatan menjijikan memberikan donasi bagi tentara fasis Israel, IDF) memainkan perannya tanpa nostalgia murahan. Produksinya bukan Neptunes throwback, tetapi evolusi dari minimalisme yang pernah membentuk suara mereka: bass berat dan ruang hening yang menegaskan setiap bar dan setiap permainan kata mereka. Dalam “E.B.I.T.D.A.” Clipse mengubah istilah finansial menjadi hook yang menular, menunjukkan bahwa bagi mereka bahasa ekonomi dan bahasa jalanan punya gravitasi retoris yang setara. “F.I.C.O.” menambahkan Stove God Cooks pada permukaan suara yang abrasive. Sebuah world-building yang mengakui bahwa dunia kriminal bukan sekadar latar, melainkan metafor tentang nilai, moral, dan waktu yang berlalu. Ini menegaskan ulang soal persepsi lain analogi-analogi narkoba dalam rima-rima Pusha T selama ini.
Dalam komparasinya dengan Hell Hath No Fury, album yang dibangun dari amarah dan lapar muda, maka Let God Sort Em Out adalah album yang dibangun dari kehilangan, jarak, dan refleksi. Malice tidak lagi menulis bar tentang masa lalu dengan kebanggaan, tetapi dengan beban moral yang terasa nyata (ehm, pasca hijrah tentu saja), sementara Pusha T tetap mempertahankan keanggunan verbal yang kini terasa seperti sikap tenang dari seseorang yang telah berdiri terlalu lama di tepi api dan selokan bisnis-bisnis terlarang. Di “All Things Considered” tersirat kesadaran bahwa nostalgia bukan kerinduan, tetapi kelelahan emosional yang belum selesai dirumuskan.
Para tamu (Nas, Tyler, Kendrick) tidak hadir sebagai penyeimbang popularitas, tetapi sebagai bagian dari dialog antargenerasi. Tyler di “P.O.V.” terasa seperti pewaris estetika mereka, bukan sekedar cameo penanda relevansi. Kehadiran Kendrick di “Chains & Whips” memberi sinyal bahwa bahkan tokoh besar generasi baru masih membaca Clipse sebagai teks rujukan.
Album ini tidak mencari kesempurnaan; ia mencari kedalaman yang masih dapat ditambang dari bentuk rap yang diperketat. Let God Sort Em Out tidak mencoba menjadi Hell Hath No Fury kedua, dan justru karena itu ia berhasil. Album ini adalah bukti bahwa rap dapat menua tanpa kehilangan relevansi, asalkan kata-kata, ritme, dan ruang terus bekerja. Tidak sebagai nostalgia, namun sebagai bentuk yang tetap bertahan, bahkan ketika zaman beralih terlalu cepat.
De La Soul — Cabin in the Sky
Jika Let God Sort Em Out membuka tahun 2025 dengan ketegangan gelap dan presisi lirik, Cabin in the Sky bergerak dari arah berlawanan: album yang mengambil duka sebagai bahan baku, tetapi membentuknya menjadi ruang hangat, bukan kuburan sunyi. Ketika De La Soul kembali setelah sembilan tahun sejak And the Anonymous Nobody…, banyak yang bertanya apakah mereka masih bisa berbicara dalam bahasa zaman yang berubah cepat. Jawabannya hadir dalam bentuk karya yang tidak sekadar album baru, tetapi ritus perpisahan dan keberlanjutan, ditenun dari kehilangan Trugoy the Dove pada 2023. Ini mengingatkan saya pada album terakhir A Tribe Called Quest pasca ditinggalkan Phife Dawg.
Dari awal, Cabin in the Sky menegaskan diri sebagai ruang antara hidup dan mati. Skit pembuka dengan suara Giancarlo Esposito terasa seperti pintu yang terbuka ke wake; sebuah pertemuan setelah kepergian. Ketika nama Dave disebut dan keheningan menyusul, pendengar segera tahu bahwa album ini tidak dimaksudkan sebagai katalog lagu, tetapi ruang bersama di mana memori, musik, dan persahabatan saling menjaga. Sekaligus juga pertanyaan bagi kita, fans De La Soul, apakah ini akan menjadi album terakhir mereka?
Secara sonik, album ini berdiri di titik pertemuan antara nostalgia dan regenerasi. De La Soul tetap setia pada permainan estetika yang membentuk mereka sejak akhir 1980-an; lapisan humor, referensi budaya, dan permainan kata. Namun kini dibalut oleh kesadaran waktu dan kehilangan. “Day in the Sun (Gettin’ Wit U)” menggabungkan boombap cerah dan neo-soul seolah menyatakan bahwa kegelapan tidak harus membekukan cahaya. “Cruel Summers Bring FIRE LIFE!!” menghadirkan pop-funk modern lewat vokal Yukimi Nagano, menunjukkan bahwa De La Soul tidak mengurung diri pada ranah nostalgia. Dan ketika mereka menggandeng Nas pada “Run It Back!!”, terasa bagaimana narasi warisan budaya kulit hitam masih menjadi sumbu tematik yang relevan tanpa harus terdengar menggurui.
Yang membuat album ini menonjol bukan hanya variasi musikalnya, tetapi cara ia memproses duka menjadi energi kreatif. Posdnuos menulis dengan kejujuran yang tenang: tentang usia, kehilangan, dan keberlanjutan sebagai tanggung jawab. Trugoy tidak hadir sebagai fragmen suara masa lalu, tetapi sebagai bagian integral dari narasi. Enam versenya terdengar seperti ia masih berada di studio, bukan dalam hardisk. Terutama pada penutup “Don’t Push Me”, di mana ringan dan tawa dalam suaranya justru membuat kehilangan terasa lebih dalam, seolah mengingatkan bahwa duka tidak menghilangkan keceriaan, hanya menempatkannya dalam konteks baru.
Para produser legendaris seperti DJ Premier dan Pete Rock membawa lanskap sonik yang klasik, sementara Supa Dave West menambahkan lapisan gospel dan organ yang mengangkat album ke arah spiritual, keduanya hadir tanpa menjadi beku dan kaku. Cabin in the Sky memang panjang (lebih dari 70 menit dan 20 trek) tetapi ia memelihara satu garis emosional yang konsisten, meski saya merasa beberapa interlude masih bisa dipangkas tanpa mengganggu efek keseluruhan.
Pada akhirnya, Cabin in the Sky bukan karya yang mencoba mengejar zeitgeist, ia menjadi album yang memilih untuk hidup dalam percakapan panjang antara memori dan masa kini. De La Soul menunjukkan bahwa hip hop tidak harus meninggalkan akar untuk berbicara tentang masa depan; justru akar itulah yang menjadi sumber kehidupan baru. Di tahun yang penuh dengan kembalinya para pelopor, Cabin in the Sky berdiri tidak sebagai penghormatan monumental, tetapi sebagai dokumen cinta, kehilangan, dan kemungkinan. Sebagai sebuah ruang di mana suara yang telah pergi tetap bernapas, dan mereka yang ditinggalkan senantiasa menjaga kehangatan yang tersisa.
billy woods – GOLLIWOG
GOLLIWOG adalah album horror yang bukan dalam tradisi Gravediggaz, Necro atau sejenisnya. Ia adalah album horor yang tidak menakut-nakuti, hanya mengingatkan bahwa kita memang sudah ketakutan sejak awal. Woods memilih jalur lain dalam mengekspos ketakutan; menutup ventilasi, mematikan lampu, dan membuat kita mendengar diri sendiri bernapas terlalu keras.
Tekanan itu dimulai dari pembuka “Jumpscare.” Judulnya menjanjikan teriakan, tetapi woods memberi yang sebaliknya: sunyi yang menggerus. Ia tidak meninggikan suara atau mengejar efek teatrikal; ia terdengar seperti seseorang yang membacakan laporan kematian tanpa ekspresi. Para produser (The Alchemist, Preservation, Kenny Segal, El-P, Conductor Williams, DJ Haram, Shabaka Hutchings, dan lainnya) menciptakan atmosfer, bukan beat. Bukan hal aneh jika kalian konsumen tetap rilisan Woods, Elucid atau kolektif mereka; Armand Hammer. Suara logam, dengung listrik, nafas pipa tua, piano rapuh yang terus kembali meneror seperti memori yang tak selesai. Tidak ada klimaks; hanya rasa waspada yang terus menerus hadir.
Saya selalu menyukai cara woods menulis, bahkan nyaris kagum. Di album ini seolah ia menulis kelelahan yang bukan moral atau sikap, tetapi dalam bentuk dunia yang terus menekan. Di “Misery,” piano Kenny Segal terdengar seperti ingatan yang ogah beranjak, woods tidak menampilkan heroisme, hanya bertahan dalam luka yang sudah terlalu lama ia gotong. “Waterproof Mascara” menambahkan jeritan terdistorsi yang ditahan di belakang beat, seakan trauma itu sendiri mencoba keluar, tapi woods menahannya dengan bahasa yang tidak menawarkan penghiburan.
Kolaborasi pada album ini bukan pertunjukan kekuatan, tetapi lebih mirip seperti kumpulan ritual. Di “Corinthians,” di atas musik post-apokaliptik khas EL-P, woods dan Despot terdengar seperti suara lain dalam cipher rahasia. Kata-kata yang mereka dilemparkan bukan untuk memukau, tetapi untuk menyimpan sesuatu agar tidak hilang. “All These Worlds Are Yours” terasa seperti ruang industri yang terendam air, dan woods berjalan di dalamnya bukan sebagai performer, tetapi penjaga reruntuhan. Di “Lead Paint Test,” kehadiran ELUCID dan Cavalier menebalkan atmosfer, tidak bertugas memberi kemegahan, meski kita tahu ELUCID baru saja memberikan kita sebuah album solo avantgarde yang megah tahun lalu.
Tema horor dalam GOLLIWOG bukan estetika visual, tetapi pengalaman kolektif yang diwariskan meski woods tidak menawarkan narasi lengkap. Jika kalian cukup sabar duduk dan mendengar album hipnotik ini, kalian bisa bilang jika bar-nya terfragmentasi seperti foto TKP yang sudah dicuci ulang. Kita tidak diarahkan untuk memahami, hanya diminta bertahan. Di situ justru sisi brengseknya, sekaligus keistimewaannya. Di penutup “Dislocated,” di atas track HUMAN ERROR CLUB, woods bersama ELUCID memberikan citra dunia terasa kosong namun penuh bekas-bekas suara, seakan album ini menunjukkan bahwa kita sudah hidup di dalam ketakutan jauh sebelum menyadarinya. Jika ini terdengar seperti track Armand Hammer sisaan albumWe Buy Diabetic Test Strips, kalian tidak sendirian.
Dalam lanskap hip hop 2025, GOLLIWOG berdiri sebagai testamen bahwa banyak kemungkinan-kemungkinan bentuk baru hip hop hari ini yang tidak hanya melulu ngerap nyanyi 4 bar dikoneksikan dengan autotune. Bahkan eksperimen itu merekam apa yang sudah lampau dan memprediksi masa depan, meski horror yang didapat.
Armand Hammer & The Alchemist – Mercy
Armand Hammer adalah proyek yang, selama lebih dari satu dekade, telah menegaskan dirinya sebagai salah satu suara paling tajam dan konsekuen dalam hip hop abstrak. Dibentuk oleh duo billy woods dan ELUCID, Armand Hammer sejak awal menolak kompromi sonik dan tema dangkal, justru memilih menyelami bebatuan keras pengalaman, sejarah, dan kondisi manusia kontemporer. Mercy, album kolaborasi mereka dengan produser The Alchemist yang dirilis pada November 2025 melalui Backwoodz Studioz, bukan sekadar lanjutan dari karya sebelumnya, tetapi pernyataan estetika yang menguji batas antara bahasa, pengalaman, dan realitas yang menghimpit.
Haram (2021) adalah pintu masuk The Alchemist ke dunia Armand Hammer, dan saya sama sekali tidak menyangka akan ada kelanjutannya. Namun di Mercy, visi yang mereka bangun di Haram bukan hanya dipertahankan. Kali ini ia menyatu dengan keyakinan yang lebih terfokus. Bayangkan Death Certificate milik Ice Cube, pasca AmeriKKKa’s Most Wanted. Pendekatan produksi tetap berbeda dari kebanyakan rap kontemporer yang didominasi kilau modern dan ritme siap-konsumsi. The Alchemist (yang di 2025 seolah kesurupan, merilis kolaborasi beruntun) kembali dengan prinsip dasarnya; tidak mengejar “kesempurnaan sonik.” Ia memilih palet yang tidak stabil, bahkan kadang sengaja tidak selesai. Efek suara yang menahan napas terlalu lama, drum tumpul yang terdengar seperti denyut sisa boombap yang gagal menjadi boombap, loop dan piano yang bergeser setengah langkah dari pusat nada, semuanya menciptakan rasa ketegangan kronis, bukan kejutan sesaat.
Lirik woods dan Elucid bergerak seperti pantulan memori kolektif: kekerasan sistemik, dehumanisasi, kecemasan teknologi, beban ras dan sejarah, semuanya hadir tanpa garis besar naratif. Mercy tidak menawarkan plot, tetapi menginventarisir emosi tentang apa yang terjadi ketika ancaman global, informasi berlebih, dan kehidupan domestik bertabrakan. Nasib seekor anjing, suara pemanas ruangan, menyiapkan sarapan anak; semua detail kecil yang berubah menjadi penanda bahwa hidup berjalan meski dunia acak-acakan luluh lantak.
Apa yang membedakan Mercy dari banyak karya Armand Hammer sebelumnya adalah urgensi yang lebih terasa di setiap bar. woods menulis dengan ketajaman non-kompromi, merangkai sejarah dan pengalaman kolektif ke dalam ayat-ayat yang nyaris terasa seperti laporan medan perang. ELUCID, di sisi lain, bergerak dalam lanskap metafisik. Ia membelok-belokkan fakta, perasaan, dan memori menjadi serpihan yang berputar tanpa titik henti. Kolaborasi mereka memang bukan soal dua gaya berbeda yang bertemu. Mereka bukan M.O.P atau EPMD. Kadang keduanya hadir seperti percakapan tajam, tak jarang seperti kontradiktif, tentang kondisi zaman yang seakan-akan diserang dari segala arah. Ketika Elucid bertanya “What’s life without wartime?” kita diingatkan bahwa hip hop bukan sekadar genre musik, melainkan cara untuk menafsirkan dunia yang terus berubah dengan cara brutal. Seperti grindcore.
Lagu favorit saya adalah “Peshawar”, di atas musik catchy (tumben banget, mas Alche), woods ngerap; Gleefully watching the system crash / No matter, though, they easily reboot it.” Ia merangkum salah satu ketegangan paling mendasar dalam imajinasi politik kontemporer: kegembiraan menyaksikan keruntuhan simbolis kekuasaan sekaligus kesadaran pahit bahwa sistem (imperium, negara, modal, korporasi) memiliki kemampuan regeneratif yang nyaris tanpa akhir. Ia menyinggung bagaimana fantasi revolusioner sering berhenti pada level afektif: euforia menatap reruntuhan, merayakan retaknya struktur, merasa bahwa sejarah akhirnya beringsut ke arah pembebasan; namun jalur material kekuasaan justru bekerja sebaliknya.
Dalam dua bar pendek ini, woods membalik mitologi “hari setelah revolusi” menjadi siklus yang tak banyak berubah: keruntuhan bukan penutup, melainkan jeda; kehancuran bukan pembebasan, melainkan reboot. Kritiknya tidak hanya diarahkan pada sistem yang keras kepala bertahan, tetapi juga pada kita yang kadang terlalu cepat menafsirkan runtuhnya bangunan sebagai akhir dari logika yang membangunnya. woods menegaskan bahwa imajinasi radikal tanpa strategi hanya menawarkan momen kegirangan, bukan transformasi; sistem bisa runtuh secara spektakuler, namun tetap kembali hidup karena infrastruktur kekuasaan tidak hanya berdiri pada gedung dan institusi, tetapi juga pada kebiasaan, komoditas, dan hasrat yang terus direplikasi. Familiar?
Namun demikian, secara keseluruhan Mercy bukan monolit gelap. Alchemist sesekali membuka celah kecil untuk humor sonik dan disonansi spiritual: gospel terdistorsi pada “Calypso Gene,” atau psychedelic soul pada “California Games” yang menghadirkan Earl Sweatshirt sebagai suara yang santai namun tetap terhitung dalam tekanan. Ketegangan berganti variasi.
Sebagian kritik menilai Mercy kurang eksplosif dibanding karya Armand Hammer sebelumnya, produksinya dianggap repetitif, teksturnya terlalu terkendali. Namun justru bagi saya, ini adalah format album Armand Hammer terbaik. Di atas musik yang terdengar terkontrol itulah kata-kata menjadi pusat, tidak bersaing dengan musik dalam menghadirkan kekacauan. Seperti katalog mereka sebelumnya, album ini tidak mengejar puncak, ia menetapkan tekanan konstan dan menunggu siapa yang berani tetap berada di dalamnya. Mereka yang sanggup akan dianugerahi kegelisahan permanen sejenis yang ditawarkan El-P di Fantastic Damage dua dekade lampau.
Apathy – Mom & Dad
Apathy sudah saya anggap sebagai salah satu MC favorit sepanjang masa. Katalognya sestabil skema rima multisilabelnya. Tak peduli apapun mood musik boombap yang melatarbelakanginya; dari yang gahar dan mengancam seperti The Widow’s Son dan King of Gods No Second, atau yang super laid back seperti album barunya, Mom & Dad. Dirilis pada bulan Juni 2025 melalui Dirty Version Records / Demigodz Records, MC veteran dari New York dan figur sentral dalam kolektif Demigodz ini kembali menunjukkan kekuatan rap naratif dengan detail kehidupan personalnya yang dibungkus teknik rap paripurna.
Mom & Dad bisa dibilang merupakan albumnya yang paling intim dan introspektif. Bukan album konseptual abstrak atau album comeback dramatis, tetapi sebuah eksplorasi relasi personal, tanggung jawab, nostalgia, dan ketegangan antara masa lalu dan masa kini. Semua dibingkai melalui pengalaman Apathy sendiri sebagai anak, ayah, dan figur yang telah mengalami banyak fase hidup. Pendekatan ini memberi album nuansa yang berbeda dari banyak rilisan 2025 yang cenderung berpikir besar; Mom & Dad justru melihat ke dalam dengan ketelitian dan keterusterangan.
Secara musikal, album ini masih mengakar pada boombap klasik, tetapi dengan tekstur produksi yang lebih matang jika tidak bisa disebut lebih santai. Produsernya tidak hanya menciptakan beat yang menghormati tradisi rap tahun 1990-an, tetapi juga menambahkan elemen harmoni yang lebih lembut dan reflektif, sebab ini adalah album yang banyak berbicara tentang hubungan, memori, dan pengalaman keluarga. Instrumen seperti piano, pads yang hangat, dan elemen turntablism halus memberi ruang bagi narasi vokal Apathy untuk “bernafas” secara emosional dan sekali lagi; naratif.
Tema sentral Mom & Dad adalah konfrontasi dengan pengalaman masa kecil dan tanggung jawab sebagai orang tua. Ini adalah materi rap yang sering nyerempet klise. Tapi Apathy berhasil membahas nostalgia dengan melampauinya; memetakan kembali potongan memori yang kompleks. Kadang pahit, kadang lucu, dan kadang diselimuti pertanyaan tentang identitas dan pilihan. Lagu-lagu seperti “Father Time” dan “Checklist” menanggapi topik keseimbangan antara hidup kreatif dan tuntutan sebagai orang tua, menampilkan MC yang tidak takut membicarakan keraguan, kelelahan, dan ketidaksempurnaan dirinya secara jujur. Hal ini memberi album rasa kedewasaan yang lebih grounded dibanding banyak rilisan hip hop di 2025 yang masih berkutat di antara gaya hidup konsumtif dan pencitraan besar.
Ia mampu memadukan cerita personal dengan observasi sosial, memberi ruang bagi pendengar untuk melihat narasi rap bukan hanya sebagai cerita jalanan, tetapi sebagai cerita hidup, yang sering kali jauh lebih rumit dan penuh lapisan daripada sekadar bars berteknik jenius atau punchline. Perpaduan antara kejujuran personal dan keahlian teknis menjadi ciri khas album ini, tanpa kehilangan kedalaman emosional. Menunjukkan bahwa hip hop tetap menjadi medium kuat untuk cerita dan refleksi kehidupan.
Uniknya, Mom & Dad membingkai kisah personal dalam lanskap sejarah yang lebih luas. Sampul bergambar Ronald dan Nancy Reagan bukan sekadar gimmick visual, melainkan penanda zaman: era Reaganisme yang membentuk atmosfer politik, ekonomi, dan moral di mana ia tumbuh. Sebuah periode yang memproduksi retorika keluarga tradisional sambil mendorong kebijakan keras kepala yang melahirkan mass incarceration, war on drugs, dan stratifikasi sosial yang makin tajam. Dalam konteks demikian, ia tidak hanya dibesarkan oleh orang tua biologisnya, tetapi juga oleh rezim nilai yang konservatif, penuh paranoia moral, dan otoritarian dalam praksis. Jika hip hop adalah medium untuk mencatat hidup sebagaimana ia dijalani (bukan sebagaimana ia dibayangkan) maka Mom & Dad menjadi salah satu testimoni paling jujur di 2025: memoar sonik yang memperlihatkan bagaimana sejarah publik meresap ke ruang domestik, dan bagaimana suara seorang MC dapat menjadi arsip alternatif terhadap narasi negara.
Saba & No I.D. – From The Private Collection Of Saba And No I.D.
From The Private Collection Of Saba And No I.D. hadir di bulan Maret 2025 sebagai pertemuan lintas generasi yang langka antara Saba (salah satu suara paling reflektif dari Chicago modern) dan No I.D., produser veteran yang menjadi tulang punggung suara kota itu sejak era Common dan Kanye West. Album ini tidak terdengar seperti kolaborasi spontan, melainkan hasil percakapan panjang dan rasa saling percaya yang tumbuh sejak sesi 2022, ketika kumpulan lagu yang awalnya diniatkan sebagai mixtape berkembang menjadi karya penuh karena kualitasnya terus menanjak.
Alih-alih mengejar intensitas atau kejutan sonik, From The Private Collection memilih jalur yang seintim judul albumnya; menandai ambisi konseptual: bukan sekadar kumpulan lagu, tetapi arsip pengalaman pribadi dan sejarah lokal yang diperlakukan seperti karya seni. No I.D. (figur yang konon menjadi inspirator Kanye West dalam mengulik soul) membawa produksi yang konsisten dengan karakteristiknya; sampledelia yang padat, tekstur jazz dan soul yang tidak berlebihan, harmoni halus yang tidak memaksa diri tampil. Sementara Saba mengisinya dengan lirisisme yang menggabungkan detail intim dan pembacaan sosial Chicago sebagai organisme hidup bukan sekedar susunan beton kaku.
Track pembuka “Every Painting Has a Price” menjelaskan metode album ini: produksi yang hangat, tidak padat, memberi ruang bagi narasi Saba yang tenang, retoris, dan penuh rasa. Kolaborator seperti BJ The Chicago Kid dan Eryn Allen Kane tidak diberikan momen teatrikal, tapi di situ istimewanya; mereka menambah lapisan emosional tanpa merampas fokus. Album ini sering terasa seperti kanvas hidup, alih-alih menekan pendengar dengan hook besar, ia mengalir dengan kesabaran, menyusun mood yang mencerminkan waktu dan tempat.
Lirik Saba bergerak antara introspeksi dan kartografi emosional Chicago. Track seperti “Westside Bound Pt. 4” memperlakukan kota sebagai sumber identitas dan sekaligus pewaris sejarah; momen kecil kehidupan sehari-hari (keluarga, sahabat, rutinitas) ditangkap seperti foto arsip yang tidak pernah berhenti berkembang. Dalam “head.rap,” muncul kilasan humor dan keringkasan naratif yang semakin menguatkan sisi manusiawi album ini, tanpa keluar dari kedalaman tematiknya.
Kontribusi tamu (dari Smino, Kelly Rowland, Raphael Saadiq, Ibeyi, hingga anggota Pivot Gang) hadir sebagai warna tambahan yang terikat pada satu visi: menjadikan hip hop bukan sekedar pameran kemampuan, melainkan media naratif yang hidup. Tidak ada kolaborasi yang terasa tempelan.
Ini sejenis album yang bisa kalian putar kapanpun dan menjadi penting karena koherensi dan ketepatan arahnya. Ia memberikan dampak melalui kedalaman, kesabaran, dan penguasaan bentuk. Sebuah bukti bahwa hip hop tetap mampu menjadi medium intim dan reflektif, bahkan ketika lanskapnya dipenuhi dorongan untuk bergerak cepat.
Di antara berbagai rilisan hip hop tahun 2025, From The Private Collection Of Saba And No I.D. berdiri sebagai kerja telaten menenun craft dengan ketenangan refleksi namun berdampak kuat lewat kedalaman dan struktur. Ia tidak hanya menunjukkan keahlian penulisan lirik dan produksi, tetapi juga mempertegas bahwa hip hop, di tangan para pengrajin yang memahami sejarah dan ruang pribadi, masih bisa menjadi medium naratif yang halus, jujur, dan sangat memikat. Tidak heran jika album ini tercatat di banyak daftar “terbaik tahun ini.”
Mobb Deep – Infinite
Infinite berdiri sebagai salah satu momen yang tak hanya paling ditunggu tapi juga paling emosional dan monumental dalam kalender hip hop 2025. Dirilis pada 10 Oktober 2025, album ini bukan hanya comeback setelah lebih dari satu dekade tanpa rilisan penuh, tetapi juga menjadi pernyataan akhir dari duo legendaris Queensbridge tersebut. Sebuah penghormatan kepada Prodigy yang telah tiada sekaligus penegasan bahwa musik Mobb Deep tetap relevan dan kuat di masa kini. Infinite adalah album ke-9 mereka dan sekaligus bagian dari deretan ikon pada proyek Mass Appeal, Legend Has It…, tahun ini. Sebuah proyek ambisius yang menyatukan karya baru dari ikon-ikon hip hop klasik seperti Slick Rick, Raekwon, Ghostface Killah, De La Soul, Big L, dan Nas & DJ Premier.
Proyek ini memadukan vokal Prodigy yang direkam sebelum kepergiannya pada 2017 dengan produksi Havoc dan kontribusi The Alchemist (Ya, lagi-lagi si Al). Namun alih-alih membentuk album pascakematian yang terasa museumistik atau sekadar kompilasi kenangan, Infinite diberi bentuk naratif utuh, membuat suara Prodigy hadir sebagai bagian hidup dari musik, bukan jejak dari arsip vokal yang belum dirilis lalu ditempelkan begitu saja. Ia terdengar seperti berbicara dari sisi lain waktu; lirik-liriknya mengekalkan ketajaman yang selama ini menjadi ciri khasnya, sementara Havoc menyatukan semuanya dengan ketelitian emosional yang terasa seperti dialog terbuka antara masa lalu dan kini.
Secara tematik, Infinite menarik pendengar kembali ke teritori Mobb Deep yang selalu basah darah: Queensbridge sebagai medan, persaudaraan sebagai sumpah yang bisa patah kapan saja, dan realitas jalanan yang tidak pernah dijual sebagai mimpi. Seringnya sebagai konsekuensi. Itu semua sangat New York. Tapi seperti The Infamous, kerasnya kehidupan di satu kompleks kelurahan bisa terdengar seperti bahasa siapa saja yang pernah bangun dengan punggung menempel pada dinding. Sesuatu yang universal. Kali ini dibingkai oleh jarak dan kehilangan, membuat beberapa bait terdengar seperti pengakuan diri yang dipantulkan lewat mikropon yang masih hangat. Prodigy tidak muncul sebagai artefak, tetapi sebagai suara yang tajam dan penuh kehadiran. Sebuah prestasi yang jarang dicapai album posthumous mana pun.
Produksi Infinite mempertahankan DNA Mobb Deep tanpa menjadi tiruan masa lalu. Havoc mengambil alih sebagian besar beat, menghadirkan drum berat, bass, dan sampel bertekstur gelap yang menjadi ruang resonansi bagi vokal. The Alchemist menambah kedalaman atmosfer tanpa merusak keseimbangan, memperkuat nuansa grimey yang tidak pernah berhenti menjadi inti estetika duo ini. Pendekatan ini membuat album terasa klasik tanpa tenggelam dalam nostalgia dan replikasi, memberi ruang bagi pendengar merasakan kesinambungan. (Meski jujur, sebagai fans Mobb Deep, selalu ada keinginan mereka mereplikasi gedoran nihilistik The Infamous)
Beberapa lagu menangkap kemistri duo ini dengan cara yang terasa organik. “The M. The O. The B. The B.” dan “Mr. Magik” mempertemukan kekuatan lirik Prodigy dengan beat yang memberi ruang bernapas sembari menjaga tekanan. Fitur-fitur tamu seperti Big Noyd, Nas, Ghostface Killah, dan Raekwon hadir sebagai perpanjangan sonic dan narasi, bukan gimmick nostalgia. Bahkan ini berlaku untuk kolaborasi Clipse yang lebih tidak terduga.
Banyak yang menyebut Infinite sebagai rilisan Mobb Deep terkuat sejak awal 2000-an, meski tidak menyamai puncak The Infamous atau Hell on Earth, saya sepakat. Kritik kecil saya hanya terletak pada seragamnya tempo. Saya tak banyak menemukan mid tempo era 3 album pertama mereka di sini, namun tidak mengurangi nilai keseluruhan album.
Dalam konteks Legend Has It…, Infinite menutup rangkaian album legenda yang tidak sedang mengulang sejarah, tetapi membawanya ke ruang hari ini. Di antara album hip hop terbaik 2025, Infinite bukan sekadar penutup layak bagi sebuah bab; ia adalah pernyataan bahwa kehadiran Prodigy tidak benar-benar pergi, ia beresonansi, menandai, dan terus bergerak bersama waktu.
McKinley Dixon – Magic, Alive!
Saya tidak memperhitungkan sama sekali jika McKinley Dixon akan datang dengan salah satu rilisan hip hop paling naratif tahun ini. Magic, Alive! adalah album kelimanya yang dirilis 6 Juni 2025 melalui City Slang, album ini tidak sekadar menambahkan bab baru dalam diskografi Dixon, tetapi memperluas apa yang ia bangun sejak For My Mama and Anyone Who Look Like Her (2021) dan Beloved! Paradise! Jazz!? (2023): jazz rap yang tidak dijadikan estetika semata, melainkan medium untuk memproses kehilangan, persahabatan, ingatan, dan cara sesuatu tetap hidup setelah tiada.
Album ini berputar pada kisah empat anak yang kehilangan seorang teman, sebuah metafora besar tentang hubungan dan duka, sebuah imajinasi bagaimana kita mencoba “membawa kembali” seseorang, dan apa yang sebenarnya kembali ketika tubuh tidak lagi ada. Dixon tidak menarasikannya secara linear; ia memberikan serangkaian momen dan potret perasaan yang membentuk satu pengalaman utuh. Magic, Alive! lebih seperti kumpulan adegan emosional yang terhubung oleh pertanyaan yang sama: bagaimana kita merawat yang hilang?
Secara musikal, album ini adalah karya paling berlapis dalam katalog Dixon. Instrumentasi live (saxophone, bass, drum, piano, bahkan harp) membangun nuansa jazz yang tebal namun tetap poros pada beat hip hop yang kokoh. Dixon tidak memosisikan jazz sebagai latar; ia membiarkannya mengatur napas album. Track seperti “Listen Gentle” dan “Sugar Water” (bersama Quelle Chris dan Anjimile) memperlihatkan bagaimana groove hangat bisa menahan ketegangan emosional tanpa meletup. Elemen rap tetap terjaga, tetapi instrumenlah yang juga berperan menuliskan gema panjang pengalaman. Di situ letak kekuatan album ini bagi saya; pada bagaimana musik dan lirik bekerja sebagai satu kesatuan.
Lirik Dixon bergerak seperti monolog personal yang sesekali berubah menjadi observasi kolektif. Chicago, keluarga, komunitas, trauma kecil sehari-hari, semuanya hadir tanpa hiperbola. Beberapa lagu terasa seperti jurnal ingatan; yang lain seperti doa untuk masa lalu yang tak berhenti meminta diingat. Kolaborator seperti Blu, Shamir, Pink Siifu, ICECOLDBISHOP, dan Teller Bank$ memberi perspektif tambahan tanpa memecah fokus; kontribusi mereka terdengar sebagai bagian dari percakapan yang sama, tidak sekedar cameo dekoratif.
Dalam lanskap hip hop 2025, Magic, Alive! memilih kedalaman, kesabaran, dan perhatian penuh sebagai kanvas. Ia menegaskan bahwa jazz rap masih mampu menjadi sarana eksplorasi emosional yang nyata, dan bahwa hip hop tidak harus berteriak untuk terdengar. Dixon menyampaikan bahwa sesuatu tetap hidup karena kita terus membicarakannya, menyanyikannya, dan memeluk kenangannya. Magic bukan trik, tetapi kerja perasaan.
Evidence – Unlearning Vol. 2
Setiap kali Evidence merilis album, saya selalu bersiaga. Kiprah solonya semakin hari semakin cantik dan melampaui apa yang ia buat bersama unitnya dulu, Dilated People. Unlearning Vol. 2 menandai kembalinya Evidence sebagai salah satu suara paling stabil dan reflektif di hip hop dua dekade terakhir. Dirilis di bulan Agustus melalui Rhymesayers Entertainment, album kelima ini melanjutkan arah yang sudah dibuka Unlearning Vol. 1 (2021): membongkar kebiasaan kreatif lama bukan untuk menemukan “hal baru” secara sensasional, melainkan untuk kembali melihat esensi rap sebagai praktik pengamatan hidup yang tajam dan rendah hati. Evidence tidak peduli dengan redefinisi genre; ia membuktikan bahwa konsistensi adalah bentuk inovasi tersendiri. Ketika ia hadir dengan rap super pelan bertempo 60 BPM bercerita tentang bercermin di genangan air hujan, saya sudah tidak lagi menganggap ia sebagai MC battle yang pernah men-diss Eminem di dua dekade lalu.
Dari judul albumnya saja kita bisa melihat bahwa Ev menolak sesuatu yang linear. Konsep unlearning yang ia tawarkan bukan nostalgia dan bukan regresi. Ia memilih struktur lagu yang ringkas, minim hook, durasi pendek, dan alur yang tidak memaksakan klimaks. Seperti album-albumnya di satu dekade terakhir, itulah ruang tempat Evidence menempatkan kekuatan naratifnya: flow yang tenang namun presisi, bar yang melingkar pada detail keseharian, dan penolakan terhadap retorika besar. Di antara rapper yang sering memprioritaskan klaim, Evidence tetap mempertahankan observasi. Ia membiarkan pendengar menemukan bobotnya sendiri. Ia tipe MC yang tidak mencoba menjadi ‘rap god’, namun sejenis lain yang memeriksa detail sekeliling dan menceritakan ulang dengan lukisan verbal beragam palet warna.
Produksi album ini menggambarkan lanskap boombap yang dusty namun matang, berkat jajaran produser seperti Sebb Bash, Beat Butcha, C-Lance, Conductor Williams, The Alchemist, Graymatter, dan QThree. Karakter musikalnya tidak berat; tetapi terkontrol, penuh grain, dan sengaja dibiarkan “kering.” Piano samar, loop jazz fusion, dan potongan sample yang tidak dipoles terasa seperti ruang kerja yang tidak pernah ditata ulang, yang justru menjaga keintiman antara beat dan bar.
Keunggulan Evidence tetap pada narasi. Di “Plans Change,” ia merumuskan kembali ambisi sebagai sesuatu yang lentur, kadang kompromi ia lihat sebagai pergeseran bukan kekalahan. “Seeing Double” menegaskan kepadatan permainan katanya, sementara fitur seperti Blu di “Stay Alive” dan Domo Genesis di “Favorite Injury” memberi aksen emosional tanpa menenggelamkan inti album. Album ini kembali memperlihatkan Evidence sebagai penutur refleksi yang tidak mencari dramatisasi.
Secara kritik, Unlearning Vol. 2 mungkin tidak dianggap terobosan besar, beberapa hiphophead menyebutnya bukan lompatan dari volume pertama. Namun, keliru jika mencari lompatan dari album-album Evidence yang memiliki kekokohan dalam eksekusinya. Ev adalah seorang veteran yang masih mampu mengatur ritme, ruang, dan nada tanpa tunduk pada formula generasi streaming. Ia tak perlu melakukan lompatan, cukup diam, menjenguk dan memeriksa. Banyak pendengar menyebutnya sebagai salah satu rilisan underrated tahun ini, album yang tidak mengejar momen viral, tetapi meninggalkan jejak panjang bagi mereka yang mendengarkan dengan sabar. Seperti halnya kerja album-album Ev sebelumnya.
Dalam konteks rilisan 2025, Unlearning Vol. 2 berdiri sebagai bukti bahwa hip hop tidak selalu harus meledak. Ia bisa bergerak dalam jeda, jeda itu berbicara, dan di dalamnya Evidence mengingatkan bahwa pertumbuhan kadang bukan “menambah,” tetapi mengurangi sampai hanya yang penting yang tersisa. Meski tidak lebih baik dari album Ev favorit saya, Weather or Not, album ini cukup impresif sebagai bagian dari betapa istimewanya hip hop di 2025.
The Expert – Vivid Visions
Vivid Visions adalah salah satu album produser paling imajinatif tahun 2025, sekaligus bukti bahwa ketika visi konseptual diarahkan dengan ketat, format “producer album” masih dapat menawarkan pengalaman naratif yang utuh, bukan sekadar etalase beat. The Expert, produser asal Irlandia dengan kecenderungan psychedelic, membangun album ini bukan sebagai kompilasi longgar, tetapi sebagai ruang mimpi kolektif: 18 trek, 21 MC, satu atmosfer yang tidak terputus, seakan seluruh album bernafas dengan satu paru-paru.
Karakter produksi The Expert tetap menjadi inti pengikat: organ yang limbung, gitar yang seolah berputar di dalam kepala, drum berdebu bersuara tegas, serta bebunyian samar yang terasa berasal dari balik kabut. Tekstur soniknya menciptakan suasana dreamlike yang langsung menguasai pendengaran, dengan transisi yang mengalir antar track sehingga album bergerak seperti satu komposisi panjang, bukan rangkaian lagu. Vivid Visions tidak menunggu hook besar atau momen klimaks; ia mengandalkan mood, lapisan suara, dan sequencing presisi untuk menarik pendengar semakin jauh di setiap rotasi.
Daftar kolaboratornya luas namun terjaga dalam orbit yang sama. Nama-nama veteran seperti Blu, Buck 65, dan Jehst berdampingan dengan suara-suara muda yang baru saya dengar (AJ Suede, Milc, Lungs, Regular Henry) dan semuanya terdengar seperti karakter berbeda dalam mimpi yang sama, bukan figuran yang lewat. Tidak ada track yang terasa tempelan; setiap MC diberi ruang untuk memasukkan visi personal tanpa mengoyak batas atmosferik yang The Expert tetapkan. “Dreams” (feat. Blu & Stik Figa) memperlihatkan keseimbangan itu dengan jelas, sementara favorit saya “Electric Kool-Aid House Band” (feat. ShrapKnel) menghadirkan energi rap yang patah, nyaris chaotic, namun tetap menyatu dengan lanskap produksinya yang berlapis.
Pendekatan soniknya mengingatkan saya pada surrealisme dalam musik: bayangan The Avalanches, gema Head milik The Monkees, sampai nuansa Lynchian yang tidak pernah disebut tetapi terasa sebagai fondasi mood yang merayap dari awal hingga akhir. Detail kecil (dialog samar, flute yang muncul sepersekian detik, bassline yang berubah arah tanpa peringatan) membuat album ini menuntut pendengaran berulang; setiap putaran membuka pintu baru dalam arsitektur suaranya.
Vivid Visions jelas bukan untuk konsumsi instan, tetapi justru di situlah ia menemukan gravitasnya. Di tengah lanskap rap 2020an yang mengejar dampak geber, The Expert merumuskan kembali fungsi album produser: bukan sekadar wadah beat, tetapi peta imajinasi bersama—padat, penuh warna, dan bernilai temuan setelah berkali-kali didengar.
Preservation & Gabe ‘Nandez – Sortilège’
Sejak pertama kali mendengar sentuhan Preservation dalam katalog Ka, saya belajar satu hal. Jika ia merilis sesuatu, maka itu bukan sekadar album tetapi peristiwa yang perlu dicermati. Preservation bukan produser “atmosferik” dalam pengertian generik. Ia tidak sekadar menyusun loop muram dan drum berdebu seperti banyak nama lain dalam lanskap hip hop bawah tanah. Yang ia lakukan adalah membangun dunia suara dengan akar yang jauh lebih dalam: mengolah sampel musik tradisional global, instrumen minor yang terdengar seperti artefak etnomusikologi, ambience yang digerus noise dan desis reel-to-reel, serta bebunyian yang terdengar seperti serpihan ritual yang dipotong dari konteksnya.
Karakternya bukan terletak pada “mood,” tetapi pada metode. Ia merepresentasikan ketekunan mengarsip, menyeleksi, lalu memampatkan referensi budaya menjadi beat yang terdengar seperti historiografi dalam bentuk sonik. Inilah yang membuat setiap karya Preservation terasa tidak pernah benar-benar tentang nostalgia atau eksotisme; ia lebih seperti kartografer yang menandai koordinat baru di dalam peta suara hip hop, di mana dunia luar tidak ditranslasikan, tetapi diselipkan apa adanya ke dalam bahasa rap.
Sortilège, kolaborasinya bersama MC bernama Gade ‘Nandez, adalah album hip hop yang beroperasi seperti ritual. Padat simbol, berlapis referensi, dan digerakkan oleh hubungan sonik–lirik yang terasa seperti mantra modern. Judulnya (bahasa Prancis untuk “sihir,” “mantra,” atau meramal melalui urutan acak) bukan sekadar konsep permukaan. Ia juga sebuah kerangka berpikir yang mengarahkan seluruh proyek. Sortilège bukan album yang ingin memukau sesaat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Album ini bekerja pelan, menembus, dan dalam durasi tertentu ia akan tinggal menetap.
Preservation dan Gabe ‘Nandez membangun relasi kreatifnya sejak “Sauvage” di album billy woods, Aethiopes (2022), dan Sortilège lahir konon ketika ‘Nandez datang ke New Orleans pada 2024 untuk merekam secara intensif. Pertemuan itu melahirkan suara yang terasa taktis sekaligus penuh intuisi: produksi musik yang menyerupai lanskap magis yang tidak stabil, bergetar, dan tidak pernah sepenuhnya terungkap; rap-nya baritonal, padat, dan menatap dunia dengan mata yang selalu terbuka dan lelah.
Preservation menata fondasi sonik yang khas: drum berderak, tekstur berdesis, reed dan gitar berakar Afrika Barat, loop yang seolah sengaja “tidak selesai”, semuanya menyusun atmosfer yang tak memberi kenyamanan. Dibuka dengan “Harmattan” yang mengembuskan nuansa gurun lewat riff gitar yang kering dan berdebu, album bergerak dimulai dengan “Spire” yang terdengar seperti sesuatu yang berada di antara meditasi dan kegeraman yang ditahan-tahan. Tidak ada beat yang berniat menjadi banger; semuanya membentuk ruang bagi suara ‘Nandez untuk mengiris perlahan.
Gabe ‘Nandez menulis rap yang bekerja di dua koordinat emosi sekaligus: pengakuan keras dan ketenangan meditasi. Flow-nya padat, sering dipotong mid-measure, membuat rima seolah mengendap sebelum menghantam pada tekanan akhir yang tak terduga di mana enjambment hadir sebagai strategi, bukan kebetulan. Baritonnya menambah bobot: kata-kata terdengar seperti objek yang dipindahkan, bukan hanya diucapkan.
Dalam urusan tema, Gabe menuliskan spektrum yang isinya merentang dari kekerasan sistemik hingga luka sejarah, tetapi ia tidak menyusun argumen linear; ia menumpuk referensi (Nebuchadnezzar, Babel, kolonialisme, nama jalan) sebagai serpihan arsip yang harus dirangkai ulang pendengar. “War” memperlihatkan bagaimana konflik menjadi pola pikir melalui pantulan media, sementara “Nom De Guerre,” bersama Ze Nkoma Mpaga Ni Ngoko, menegaskan bahwa ketahanan dan nyeri sering berbicara di luar batas Bahasa; ritmis, historis, dan sangat manusiawi.
Kolaborasi lain seperti Armand Hammer dan Benjamin Booker di “Mondo Cane” cukup berfungsi memperdalam ruang, seakan menambah asap pada ruangan yang sudah dipenuhi tanda, tidak membuka jendela-jendela baru. Sayangnya, pada lagu itu saya tiba-tiba lupa jika itu lagu Gabe ‘Nandez, Armand Hammer merampoknya.
Lepas dari makna judulnya, tema album ini sebetulnya justru bukan ramalan tetapi lebih merupakan pembacaan keadaan: dunia yang normalisasi kekerasannya membuat kita menghafal bencana sebelum memahami sebabnya. Namun pada lagu penutup “Lotus Flower”, Gabe memberi isyarat bahwa kebangkitan tidak selalu terang. Dengan indah ia bertutur bahwa bertahan hidup dalam gelap bukan hanya sebuah keharusan namun juga konsekuensi sejarah.
Sortilège berdiri sebagai karya yang menuntut pendengaran utuh. Ia bukan tipe album yang eksis untuk dilewati, namun untuk ditapaki. Preservation & Gabe ‘Nandez membuktikan bahwa hip hop tetap mampu menjadi ritual kontemporer: pengetahuan, perlawanan, dan ketahanan yang diucapkan dengan nada rendah tetapi bergema panjang.
The High & Mighty – Sound Of Market
Sound Of Market menandai kembalinya The High & Mighty setelah dua dekade tanpa album penuh, dan sejak menit pertama terdengar jelas bahwa mereka tidak pulang untuk mengenang kejayaan lampau, tidak untuk nostalgia, namun untuk menajamkan kembali bahasa yang mereka bangun sejak akhir 1990-an. Sebuah proyek berkelanjutan.
Dirilis 6 Juni 2025 oleh Eastern Conference Records, album ini menyatukan Mr. Eon dan DJ Mighty Mi dalam bentuk yang tidak berusaha menyesuaikan diri dengan rap kontemporer, melainkan memperkuat estetika lama dimana boombap berdebu, sample soul yang dipilin kasar, dan rima yang digerakkan oleh energi lokomotif. Tidak ada ilusi futurisme, tapi juga tidak ada usaha membekukan masa lalu: Sound Of Market terasa seperti rap veteran yang tahu persis apa yang mereka lakukan, dan tak menemukan alasan mengapa mereka harus berubah. Mereka tidak sedang merawat konvensi apapun, hanya memainkan yang mereka pahami.
DJ Mighty Mi menulis beat yang padat sebagai kanvas, drum yang kering namun presisi, bassline tebal yang bertindak sebagai fondasi, serta loop yang dipilih rapi tanpa kehilangan grit. Setiap komposisi memberi ruang bagi gaya Mr. Eon yang tegas, artikulatif, dan tetap lugas seperti dulu, hanya kini lebih sarat pengalaman. Pembuka “2 Man Crew” menegaskan arah album ini, tanpa intro teatrikal, tanpa hook berlebihan; hanya bars and pressure yang mengingatkan bahwa rap tidak butuh aksesoris untuk berbicara keras. Alasan yang sama dahulu pernah jatuh cinta pada Freddie Foxx atau Blaq Poet.
Daftar tamu yang berkilauan memperkuat palet tanpa membuyarkan fokus. Kool Keith memutar stream-of-consciousness khasnya di “Pinky Tuskadero,” sementara Skillz di “6ers & Squires” bertukar bait dengan Mr. Eon dengan tajam dan ekonomis. Kolaborasi lainnya—Breeze Brewin dan Your Old Droog pada “The Rose Bowl,” Large Professor dan Tash pada “Prism,” King T di “Dubbs Up”—membawa ragam tekstur namun seluruhnya tetap mengalir dalam garis besar estetika album: bars yang mendarat tepat di saku beat, groove yang mendorong kepala mengangguk tanpa paksa, dan keseimbangan antara nyawa East Coast dan napas veteran di dekade berbeda.
Beberapa bagian memang terdengar sedikit keruh dari sisi engineering, tetapi tidak sampai menggerus karakter album; justru sebaliknya, ketidaksempurnaan kecil itu terasa seperti bagian dari cara mereka merakit estetika; berangkat dari pengalaman, insting, dan craft, bukan dari ambisi polesan digital. Saya yakin mereka tidak sedang berniat membuat album lo-fi, hanya saja memiliki kesadaran bahwa tekstur yang tidak sepenuhnya licin dapat menjaga ketegangan suara dan memberi bobot pada kehadiran MC. Mereka pula tidak sedang menjual nostalgia: Sound of Market terdengar seperti musik tradisi yang dimainkan hari ini, bukan upaya membangkitkan kejayaan primordial. Mereka hanya memainkan bahasa yang mereka kuasai, dan tahu persis bahwa ketika tradisi dijalankan oleh tangan yang mengerti nilainya, ia tetap terdengar relevan, tajam, dan penuh nyawa.
Catatan kecil saya hanya pada variasi tempo: mayoritas track bergerak di bawah 80 BPM, membuat alurnya terasa terlalu konsisten. Padahal The High & Mighty punya reputasi mendorong boombap klasik ke daerah yang lebih agresif ketika tempo dinaikkan. Sedikit pergeseran ke BPM yang lebih tinggi mungkin akan memberi album ini semburan energi tambahan, bukan agar menjadi modern, tetapi agar menunjukkan kembali sisi paling fisikal dari bahasa rap yang mereka bangun sejak awal. Namun bahkan dengan kekurangan itu, Sound of Market tetap terasa seperti album yang tahu apa yang ingin dikatakan, dan merepresentasikannya tanpa ragu.
Ghostface Killah – Supreme Clientele 2
Setelah album Wu-Tang terakhir yang gagal total, rap fans selalu dapat berharap diobati oleh album-album solo anggotanya. Supreme Clientele 2 tiba pada 3 Desember 2025 sebagai salah satu jawaban sekaligus kejutan terbesar dalam kalender hip hop modern, sebuah jawaban atas mitos panjang yang selama dua dekade lebih hanya beredar sebagai rumor, sketsa ide, dan gosip studio. Dua puluh lima tahun setelah Supreme Clientele (2000) menegaskan Ghostface Killah sebagai MC visioner dengan sensibilitas naratif yang sukar disamai, sekuelnya akhirnya muncul melalui Mass Appeal Records sebagai bagian dari seri Legend Has It…: sebuah inisiatif kuratorial untuk menghidupkan kembali suara klasik dalam lanskap kontemporer tanpa menjebaknya dalam museum nostalgia.
Album ini diposisikan sebagai titik temu dua masa: warisan Wu-Tang yang membentuk estetika rap generasi awal dan hip hop 2020-an yang bergerak cepat, padat, dan hiper-bercabang. Sejak intro, Ghostface kembali menampilkan flow cepat yang asimetris, penuh image stacking, slang surreal, dan detail jalanan yang dirangkai seperti montase film noir—atribut puitik yang membuatnya unik sejak Ironman dan Supreme Clientele pertama. Terlepas dari jarak waktu, penempatan frasa, ritme internal bar, dan cara ia meletakkan kata-kata seperti serpihan ingatan tetap utuh, memperlihatkan bagaimana Sang Ironman “menua” secara teknis tanpa kehilangan listriknya.
Kolaborasi memainkan peran signifikan, tentu saja bukan sebagai dekorasi namun pengukuhan jejaring sejarah. Nas, Method Man, Raekwon, Conway the Machine, hingga Styles P memberi rentang antar-era; “Love Me Anymore” menonjol sebagai dialog dua legenda New York yang berbagi refleksi personal tanpa kehilangan ketegangan lirikalnya. Ghostface paling kuat ketika ia menangkap atmosfer dengan hanya detail konkret: sepasang sepatu, kilatan pisau, botol anggur murah, ritme napas sebelum keputusan fatal: bahasa kecil yang memperbesar dunia. Ia benar-benar murid sahih Slick Rick dalam hal ini.
Secara musikal, Supreme Clientele 2 bergerak dalam boombap bertekstur modern: soul loops yang dipotong kasar, perkusif gritty, dan sentuhan kontemporer yang tidak mengganggu pondasi. Ide mengundang breaks era hip hop 80-an juga cukup menarik. Favorit saya hadir di momen “Georgy Porgy” yang mengambil sample breaks lagu lawas Toto dengan judulnya sama, lalu “Rap Kingpin” tak hanya dengan nuansa Supreme Clientele pertama, namun pula memanggil ulang atmosfer Rakim era “My Melody” lengkap dengan drum machine menghentaknya. Track “The Trial” memberikan reuni Wu-Tang yang selayaknya dengan mengundang Raekwon, Method Man dan GZA.
Berisi 17 track, meski lagu betulannya hanya 12, sisanya hanya skit, sepertiga akhir album agak membosankan namun saya menikmati album ini. Bagaimanapun, album ini memang kadung lahir dengan beban sejarah yang tidak mungkin diabaikan: judulnya sendiri. Supreme Clientele pertama terlalu monumental; sekuelnya hampir mustahil melampaui energi visioner yang dulu terasa seperti wahyu. Evaluasinya menjadi paradoks alias serba salah. Ketika album ini bergerak aman, ia terasa kurang menggigit; ketika ia mencoba keluar jalur, ia tidak sepenuhnya jadi terobosan. Sebetulnya bukan kegagalan juga, hanya saja ia tidak memiliki dentuman kreatif yang mengubah lanskap seperti terdahulu.
Namun demikian, saya cukup puas jika pada akhirnya sekuel ini lahir, ia tidak lagi menjadi mitos dan mengakhiri rasa kepenasaran dua dekade. Kehadirannya saja sudah menyelesaikan sesuatu yang tak bisa diselesaikan oleh nostalgia: rasa ingin tahu yang akhirnya diberi bentuk. Di tahun 2025, album ini mengingatkan bahwa meskipun standar estetika berubah, karakter, diksi, dan insting dramaturgis Ghostface tetap memiliki daya magnet yang tidak dimiliki siapa pun. Ironman masih memiliki tempat yang kuat dalam percakapan musik modern.
Raekwon – The Emperor’s New Clothes
Jika Ghostface datang dengan jilid kedua magnum opusnya, saya berpikir apa yang akan dilakukan Raekwon di bawah payung Legend Has It… dari Mass Appeal. Tak mungkin ia membuat Only Built For Cuban Linx II, karena sudah ia lakukan 16 tahun lalu. Ketika The Emperor’s New Clothes dirilis akhirnya saya menemukan jawabannya dalam bentuk rasa lapar Raekwon setelah delapan tahun tanpa album solo. Sebuah rentang yang tidak sepenuhnya kosong, tetapi justru fase pemurnian.
Selama periode pasca The Wild (2017), Rae tidak pernah keluar dari percakapan kultur rap. Ia menjadi figur sentral dalam The Purple Tape Files, muncul pada sejumlah album relevan dari Griselda, dan mempertajam kembali diksi mafioso yang ia bentuk sejak Only Built 4 Cuban Linx…. Maka album barunya ini tidak terdengar seperti reuni gugup, melainkan hasil distilasi delapan tahun kerja senyap—periode di mana ia belajar menahan diri agar tahu kapan harus berbicara lagi. The Emperor’s New Clothes berdiri bukan untuk mengembalikan Rae ke puncak chart, tetapi untuk menunjukkan bagaimana seorang MC legendaris memaknai keberlanjutan dalam lanskap rap yang berubah cepat.
Secara musik, ia sudah sangat bisa ditebak meski tanpa RZA di belakang layar; komposisi yang merujuk pada East Coast rap klasik: loop soul, drum tegas, dan produksi yang mengedepankan ruang bagi alur naratif. Saya pikir ini bukan pula main aman, justru di wilayah inilah The Emperor’s New Clothes menemukan kekuatannya. DJ Fiery, Scram Jones, DamnNoise, dan No I.D. membangun beat-beat yang cukup tenang (sebuah anomaly jika melihat katalog Rae yang cenderung noir) untuk menampung bar-bar Rae yang padat referensi, tapi cukup berat untuk tetap berdiri dalam kultur boombap kontemporer.
Rae merangkai epos urban yang tidak linear namun terhubung secara emosional. “Bear Hill” membuka album dengan ketegangan hidup sehari-hari yang ia kemas seperti noir kota. “Pomegranate” bersama Inspectah Deck dan Carlton Fisk menghadirkan chemistry Wu-Tang dalam mode dewasa; tidak eksplosif, namun mapan dan setara. “Wild Corsicans” menempatkan Rae dalam cipher lintas generasi bersama Griselda; Rae tidak mencoba mengungguli mereka, tetapi menunjukkan bahwa ketahanan naratif lebih hidup daripada sekadar punchline keras, membuat Griselda tunduk pada sang innovator mafioso rap. Sementara “The Omertà”, duetnya dengan Nas, menghadirkan dua legenda New York berbicara bukan sebagai murid dan guru, tetapi sebagai dua kutub pengalaman yang saling menguji integritas.
Skit seperti “Veterans Only Billionaire Rehab” dan “Officer Full Beard” hadir bukan sebagai filler, melainkan penjepit ritmis yang menandai bab-bab dramaturgis yang Rae ceritakan. Jika ada durasi ramping beberapa trek dan tempo produksi yang terkesan datar; saya rasa itu resiko yang ia ambil setelah memilih palet estetika yang terkendali.
Album ini bukan jawaban atas masa lalu, tetapi pembuktian atas apa yang bisa dilakukan oleh suara veteran; hidup tanpa meniru dirinya sendiri, terlebih berusaha tidak menjadi parodi dirinya sendiri. Raekwon tidak datang untuk mengejutkan. Jika dideretkan, album ini tak lebih bagus dari 2 album pertamanya. Namun ia datang untuk menegaskan bahwa keberlanjutan adalah kemampuan untuk tetap relevan tanpa kehilangan bahasa asal. Di 2025, itu lebih langka daripada punchline sempurna.
Vinnie Paz – God Sent Vengeance
Vinnie Paz bisa dicatat sebagai orang yang paling keras kepala dalam konteks mempertahankan konservatisme boombap. God Sent Vengeance, album solo ke-9 miliknya, menegaskan kembali posisi tersebut; salah satu figur yang paling setia pada estetika rap keras: tanpa kompromi, tanpa gestur manis, dan tanpa upaya meredam nada suaranya demi kenyamanan publik.
Dirilis pada 3 Oktober 2025 melalui Enemy Soil Records, album ini menunjukkan bahwa veteran dua dekade lebih sejak Psycho-Social masih menyimpan amarah retoris dan kejelasan visi, bahkan ketika lanskap hip hop telah melompat dari era mixtape fisik menuju stream yang dilahap cepat dan ringan.
Secara sonik, bagi saya album ini menjadi yang terbaik darinya selama satu dekade terakhir. Ia bergerak di inti boombap gelap yang menjadi poros estetika Jedi Mind Tricks dan Army of the Pharaohs, namun dengan karakter produksi yang terasa lebih rapat dan bertekanan. DJ Premier, Ayatollah, dan sejumlah produser bawah tanah lain menciptakan beat yang bertenaga namun tak bombastis: drum yang berat, bass menekan, dan lapisan tekstur yang kadang terasa industrial. Tidak ada ruang longgar di mana setiap elemen terasa seperti dipahat untuk menahan liris Vinnie yang menghantam, bukan sekadar mengiringinya. Pendekatan ini memberi sensasi bahwa album bukan sekadar koleksi lagu, tetapi arena tempat suara Vinnie menjadi pusat gravitasi.
Liriknya memadukan kritik terhadap kekuasaan, paranoia sosial, sejarah kekerasan, serta introspeksi pahit yang ia bungkus tanpa sentimentalisme. Pada trek seperti “Scourge of the System”, ia memposisikan masyarakat sebagai ladang pertarungan moral, menyoroti bagaimana kebebasan kerap hanya slogan yang dipoles, bukan realitas yang bisa dirasakan. Suaranya yang gravelly diperlakukan seperti instrumen perkusif di mana setiap bar jatuh seperti dentuman snare berat yang menandai struktur, bukan sekadar meluncur mengikuti beat. Ironisnya, semakin ke sini teknik Vinnie Paz justru semakin menuju ke arah ekonomi kata yang ekstrem. Jika pada era Violent by Design ia masih membiarkan multisyllabic rhyme scheme mengalir panjang, kini ia sering memotong kata dan menegakkan spasi antar frasa, sehingga flow-nya terdengar seperti staccato cadence: potongan spoken-word yang dirangkai dalam ledakan pendek.
Pilihan teknis ini bukan sekadar perubahan gaya, tetapi bagian dari strategi artikulasi. Dengan mengurangi suku kata, ia memperbesar bobot setiap kata yang dipakai. Saya yakin, dalam hal ini Vinnie Paz terpengaruh oleh sang wordsmith almarhum asal Brownsville, Ka. Internal rhyme yang dulu kaya kini diganti dengan end-rhyme yang dipukul keras dan diulang polanya, memberi kesan repetisi traumatis alih-alih permainan kata flamboyan. Hasilnya flow yang terasa “berat” bukan karena kompleksitas linguistik, tetapi karena intensitas tekanan fonetik yang dipertahankan dari awal hingga akhir.
Teknik ini membuat pendengaran terasa seperti menghadapi seri pukulan pendek, bukan kombo panjang. Massa kata yang dipadatkan, bukan paragraf yang dibentangkan. Di titik tertentu, struktur bar Vinnie bergerak dari rhymed phrasing ke “hammered phrasing”: bukan lagi alur fonetik yang mengalir, tetapi serangkaian pukulan ritmis yang diperhitungkan. Ini menjelaskan mengapa rap-nya kini terdengar seperti spoken-word yang dilas menjadi rap, bukan rap yang dipoles agar terdengar puitis.
Pendekatan ini mungkin membuat sebagian pendengar lama merindukan kepadatan multisilabel khas Vinnie, tetapi justru di sini ia menemukan cara baru untuk menekan makna dan agresi ke dalam ruang bar yang semakin sempit. Meski mengorbankan keindahan cadence ala Big Pun yang ia miliki, ini membuktikan bahwa evolusi teknis tidak selalu datang dari penambahan ornamen, tetapi dari penyisihan yang teliti dan brutal.
Bukan album Vinnie jika tidak bertaburan fitur MC tamu. Dua MC Non-Phixion, Ill Bill dan Lord Goat, memberi intensitas gelap yang setara, sementara Jared Evan menyelipkan hook bernuansa melodis yang tidak melembutkan album, melainkan memberi kontras emosional. Suara-suara lainnya adalah nama-nama yang familiar; Cappadona dan Onyx misalnya. Persaudaraan Army of the Pharaoh tentu saja hadir, dari mulai Apathy, Esoteric hingga Celph Titled.
Jangan mencari yang baru dari album Vinnie. Mereka yang mencari inovasi struktural atau hook besar akan menemukan album ini terlihat ngotot. Namun mereka yang ingin ketegangan dipertahankan dari awal hingga akhir akan melihatnya sebagai salah satu rilisan paling fokus Vinnie dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada kejutan drastis, tetapi juga tidak ada kompromi: God Sent Vengeance berdiri sebagai bukti bahwa rap brutal era La Coka Nostra berkuasa masih hidup karena ada pendengar yang memerlukan suara yang tidak meredakan amarah, tidak membungkus luka dan kebusukan, dan tidak menyusun “harapan palsu” di akhir album. Dan 2025 punya banyak alasan untuk merawat itu.
Tomorrow Kings – SALT
Setelah lebih dari satu dekade berlalu sejak debut Niggers Rigged Time Machine (2013), SALT menandai kembalinya Tomorrow Kings, kolektif hip hop dari Chicago, dengan karya yang terasa sebagai pernyataan artistik matang, konseptual, dan berakar kuat dalam pengalaman kehidupan urban. Setelah periode panjang di luar sorotan utama, album ini dirilis pada awal November lalu. Menyatukan enam anggota inti (Collasoul Structure, I.B. Fokuz, Malakh El, Gilead7, Skech185, dan IL. Subliminal) dalam sebuah proyek yang lahir di masa pandemi melalui traded files dan komunikasi jarak jauh.
SALT bukan sekadar reuni, ia adalah proyek yang dirancang sebagai refleksi filosofis tentang sejarah, identitas, dan ketahanan. Tema utamanya mengambil simbol garam sebagai metafora. Garam hadir bukan sekadar rempah dapur, tetapi representasi ketahanan, preservasi, dan tegangan dalam kehidupan. Misalnya pada “The News”, I.B. Fokuz membolak-balikkan narasi Lot dalam cerita Alkitab, menyatakan bahwa “a pillar of salt is only a nigga that’s lost,” sebuah pembacaan ulang metafora yang merobek sentimentalitas menjadi komentar tajam tentang nostalgia, memori, dan kehilangan arah dalam arus sejarah dan budaya modern.
Ini muncul sejak pembuka “Regicide”, yang dimulai dengan suara anak kecil menyanyikan, “This world will never end,” sebagai semacam proklamasi sekaligus pertanyaan eksistensial. Track ini kemudian berkembang menjadi potret kolektif: setiap MC berperan sebagai alat kritik terhadap hierarki yang diwariskan dan sistem yang menindas.
Musik SALT bergerak di luar batas boombap tradisional dengan citra sonik yang lebih tekstural dan atmosferik. Sesuatu yang saya rindukan setelah Anti-Pop Consortium dan Rubberoom melenyap dari horizon musik rap. Produksi oleh Aoi memberikan lanskap yang terasa seperti post-industrial soundscape penuh dust-heavy drums, tiupan terdistorsi, dan unsur siren yang jauh di latar, menciptakan atmosfer Chicago yang keras dan penuh tantangan. Beberapa bagian bahkan terdengar seperti kereta elevasi yang melintasi rel berkarat, kasar namun penuh karakter, sementara kadang synth berpendar seperti lampu jalan yang goyah, memperkukuh suasana urban yang tidak bersahabat namun jujur. Seolah campuran antara ritme klasik kota dan tekstur naratif abstrak, setara dengan free jazz dan noir sci-fi dalam intensitas dan mood.
Yang membuat SALT berdiri kuat adalah keberagaman suara dan perspektif individual dari setiap anggota kolektif. Collasoul Structure sering menjadi jangkar naratif, membicarakan realitas sehari-hari dengan nada yang lugas dan terkadang humoris, seperti ketika ia mengungkapkan setengah cabul namun penuh sarkasme tentang kehidupan di trek-nya. I.B. Fokuz memainkan peran moral kompas, dengan bait yang mengungkapkan kelelahan kolektif dan isu-isu sosial seperti kerusuhan kota yang dipicu oleh ketimpangan kekuasaan. Skech185 lebih cenderung menjadi satiris apokaliptik, membaurkan tipuan dan tragedi dalam citra yang tajam. Sementara itu, Malakh El menggabungkan elemen mistik dan semangat militan, memberi warna filosofi dan spiritual yang berlawanan namun saling melengkapi dengan realisme lirik lainnya.
Secara tematik dan musikal, SALT sering terasa menuntut pendengar untuk terlibat secara intelektual, bukan sekadar menerima lagu sebagai latar belakang. Bahasa rap yang kaya referensi sejarah dan teologi, dikombinasikan dengan produksinya yang terkadang menantang, membuat album ini terasa seperti laporan lapangan yang filosofis dan sosial. Memuaskan secara konseptual bagi mereka yang menghargai rap dengan kedalaman tekstual dan naratif.
Album ini menempatkan Tomorrow Kings sebagai salah satu kolektif paling relevan dan berpengaruh dalam ranah hip hop progresif 2025. Sekaligus bukti bahwa rap bisa menjadi forum intelektual sekaligus artistik, sebuah ruang di mana sejarah, pengalaman urban, filsafat, dan ketahanan kolektif bertemu dan dipertanyakan ulang. Bagi mereka yang mencari hip hop politis yang memikirkan kembali sejarah dan eksistensi, SALT tetap menjadi salah satu rilisan paling substansial dan menantang tahun 2025.
Big L – Harlem’s Finest: Return Of The King
Saya selalu kembali pada satu momen kecil namun menentukan dalam sejarah rap: wawancara Nas sebelum ia masuk studio merekam Illmatic. Saat itu ia mengaku pesimis ketika mendengar Big L, bukan karena meremehkan, justru sebaliknya. “Kalau MC seperti ini yang naik nanti, apa saya bisa bersaing?” Kesaksian itu memberi gambaran seberapa menakutkannya Big L pada awal 90-an: bukan sekadar raja punchline, tetapi penulis yang mampu menautkan diksi jalanan dengan ketelitian bahasa yang nyaris literer. Ia membawa wit dan kecerdasan verbal yang biasanya diasosiasikan dengan intelektual kampus, namun ia sendiri tumbuh sebagai hustler Harlem, bukan mahasiswa perguruan tinggi. Kombinasi ini (ketajaman teknis, kredibilitas jalanan, humor yang gelap, dan sense timing yang luar biasa) menjadikannya ancaman paling serius bagi siapa pun yang ingin dianggap penulis dalam rap.
Pertanyaan yang menghantui saya (dan sebagian besar pendengar yang tahu teknik L luar dalam) selalu sama: bagaimana jika ia tidak ditembak pada 1999? Ada keyakinan tak terucap bahwa sophomore albumnya bisa melampaui debutnya, mungkin bahkan mendorong ulang hierarki East Coast saat itu. Saya tidak ragu membayangkan Big L bersanding atau bahkan melewati Jay-Z, Biggie, dan (dalam skenario tertentu) Nas sendiri. Debutnya, Lifestylez Ov Da Poor & Dangerous, terdengar seperti pemanasan dari seseorang yang baru mulai sesuatu. Ya, baru pemanasan.
Harlem’s Finest: Return Of The King adalah upaya besar untuk membawa kembali suara Big L ke percakapan hip hop 2025 melalui pendekatan kuratorial, bukan mimikri. Sebagai rilisan posthumous kelima dan bagian dari seri Legend Has It…, album ini berdiri sebagai gerbang generasi antara arsip ’90an dan lanskap modern, menghimpun freestyles, unreleased verses, dan vokal restorasi yang dirajut ulang dengan produksi baru. Karena katalog L yang terbatas (ia hanya sempat merilis Lifestylez Ov Da Poor & Dangerous semasa hidup) proyek ini memikul beban ganda: menjaga integritas liriknya sambil memberi bentuk album yang terdengar relevan dua puluh lima tahun setelah kepergiannya.
Secara konsep, Return Of The King bukan album “baru,” tetapi album “yang dibuat menjadi baru.” Trek seperti “Harlem Universal” segera menegaskan akar geografis dan aura Big L: boombap keras, swing kotor khas New York, dan fleksibilitas multisilabel yang masih menusuk. Materi lama diolah ulang agar membentuk garis naratif yang mengitari tema-tema inti Big L; identitas Harlem, bragging rights, dan struktur punchline yang presisi, tanpa menutup fakta bahwa ini kompilasi arsip yang dipoles, bukan rekaman penuh yang diniatkan.
Produksi album digarap berlapis oleh Havoc, The Alchemist, Buckwild, dan sederet nama kontemporer sehingga menciptakan rentang sonik yang luas: dari grit era Stretch & Bobbito hingga rap modern yang lebih tajam pada low-end. Sementara fitur artis menegaskan kehormatan lintas generasi; Nas, Jay-Z, Method Man, Joey Bada$$, bahkan Mac Miller. Meski keterlibatan yang disebut terakhir barusan banyak yang tidak Ikhlas. Masing-masing MC berfungsi sebagai saksi sekaligus peserta. Kolaborasi semacam “U Ain’t Gotta Chance” atau “7 Minute Freestyle” memperlihatkan kontinuitas warisan lirik L, namun juga mengungkap jarak teknologi rekaman: timbre vokalnya kadang terdengar lebih berumur dibanding track tamu yang direkam bersih.
Kekuatan inti album tetap pada bahasa Big L. Bar-nya menua tanpa melemah: punchline masih menggigit, internal rhyme padat, penempatan multisilabel presisi. Bahkan saat hanya satu verse, ia tetap memberi kesan seluruh paket yang disebut barusan. Tidak heran sebagian pendengar merasa Return Of The King menunjukkan betapa L (jika hidup lebih lama) mungkin akan menjadi rujukan teknis setara Nas atau Black Thought dalam perdebatan generasi.
Sebagai dokumen 2025, Return Of The King bukan puncak baru Big L, tetapi perpanjangan napas warisannya: kesempatan bagi generasi yang lahir setelah kepergiannya untuk mendengar ketajaman teknis yang, pada masanya, mendahului algoritma dan hype. Bagi penggemar lama, album ini adalah pengingat pahit-manis tentang legenda yang pergi tragis terlalu cepat.
Namun sebagai album posthumous, Harlem’s Finest memikul batasannya sendiri, dan batasan itu terdengar jelas. Ketidakseimbangan mixing antar-vokal, durasi pendek beberapa trek, serta fragmen verse yang terasa seperti sobekan dari buku rima yang belum sempat disusun ulang membuat struktur album ini tidak benar-benar berdiri sebagai karya hidup. Lebih tepat dibaca sebagai mixtape terkurasi atau kompilasi arsip yang dipoles seperlunya, bukan album yang dibayangkan dan ditutup oleh tangan L sendiri.
Tetapi di situlah juga letak paradoks yang tak bisa dipisahkan dari proyek ini: kekurangan teknisnya justru memperlihatkan material mentah yang L tinggalkan. Tidak dipoles, tidak disempurnakan, tidak diberi kesempatan untuk berevolusi menjadi karya utuh. Setiap bait pendek, setiap verse yang berakhir tiba-tiba, terdengar seperti pesan terputus dari seseorang yang masih memegang pena di tangannya. Kekosongan itu menyisakan ruang imajinasi, dan ruang imajinasi itulah yang paling mengerikan; bagaimana jika ia memang membuat album kedua yang sudah sangat serius? Bagaimana jika L memang sempat membuat album keduanya dengan visi penuh, energi hidup, dan penguasaan teknik yang sudah matang? Harlem’s Finest tidak menawarkan jawaban, ia justru memperkuat dahsyatnya pertanyaan itu dengan memfokuskan kembali perhatian pada teknik liriknya yang eksplosif, karakter rapnya yang tak tergantikan, dan pengaruhnya terhadap generasi MC selanjutnya, termasuk Jay Z.
Jika saya memikirkan kembali komentar Nas di awal tadi, masuk akal jika kemudian Harlem’s Finest: Return Of The King ini muncul justru melalui Mass Appeal. Ini bukan sekadar penghormatan, lebih mirip pengembalian hutang sejarah. Sebuah pengakuan bahwa Big L adalah salah satu dari sedikit MC yang membuat generasi era keemasan rap berhenti, menimbang ulang, dan bertanya: berapa banyak ruang sebenarnya yang tersisa di puncak jika L tidak pergi terlalu cepat? Album ini berdiri sebagai jawaban yang terlambat, tetapi tetap perlu. Sebuah usaha untuk menempatkan L kembali di panggung yang mungkin seharusnya ia isi sejak lama.
Killah Priest – Abraxas 2
Sejak Heavy Mental (1998), Killah Priest telah menempati posisi yang nyaris tidak tersentuh dalam hip hop. Saya pertama kali mendengarnya di penutup album mahakarya GZA, Liquid Swords, dan sejak itu selalu memburu apa yang ia buat. Ia bukan sekadar lyricist yang jenius, bukan hanya anggota orbit Wu-Tang dengan jaringan kolaborasi luas, tetapi figur yang menjadikan rap sebagai jalur ziarah. Ia bergerak di garis yang jarang ditempuh para rapper; antara eksoterisme jalanan dan esoterisme spiritual, menjadikan bait rapnya sebagai wahana tafsir kitab, sejarah, dan memori kolektif kulit hitam. Di era ketika Wu-Tang meledakkan imajinasi publik lewat sample kung-fu, mitologi Staten Island, dan slang yang mendistorsi bahasa Inggris, Priest memilih jalur lebih sunyi namun memiliki kedalaman: membentuk persona MC sebagai penjaga naskah, bukan sekadar pencerita.
Warisan itu tidak pernah hilang. Jika GZA dikenal karena presisi logika, Ghostface karena imaji dan metafora flamboyannya, Priest berdiri sebagai nabi tak resmi, penyebar skrip yang menggabungkan genealoginya dari Five Percent Nation, pengaruh Kabbalah, narasi Babilonia, hingga kosmologi Afrika kuno, untuk kemudian membawa rap lebih dekat kepada bentuk kontemplasi yang biasanya ditemukan dalam teks suci, bukan dalam verse 16 bar. Itulah konteks di mana album-albumnya harus dibaca. Dan bicara soal album Priest adalah keluarga Wu-Tang yang paling produktif, merilis minimal dua album dalam satu tahun, dan semua dieksekusi dengan kedalaman yang luar biasa. Begitu pula Abraxas 2 ini, ia bukan hanya album baru, tetapi lanjutan dari tradisi yang Priest bangun selama lebih dari dua dekade; rap sebagai ritual pencarian makna.
Dirilis pada bulan September lalu, Abraxas 2 meneruskan kisah Abraxas Rebis Simha Pleroma (2024) sekaligus menegaskan bahwa Killah Priest, setelah sekian banyak album, masih menemukan cara untuk mempertajam estetika spiritual-rap yang ia bangun. Purpose of Tragic Allies kembali memproduseri album, merangkai boombap kontemplatif dengan lapisan suara ambient yang membentuk ruang dengar seperti kuil kecil: sunyi, tidak steril, meditatif, penuh denyut.
Tekstur musiknya rapat dan fungsional, beat dan instrumen tidak pernah berdiri sendiri, melainkan mengantar frasa Priest. Bahkan ketika yang hadir hanya ambient. Ia bercerita melalui referensi yang luas, tetapi seperti halnya beberapa karyanya belakangan, Priest semakin menemukan bentuk rimanya yang memiliki alur lebih cair, bait tidak lagi terdengar seperti katalog istilah, dan lebih terdengar sebagai kontinuitas pikiran. Priest berbicara seolah sedang menafsir ulang kitab dalam dirinya sendiri, bukan hanya sejarah yang ia baca.
Tentu saja butuh metode mendengar dan menyimak karyanya secara berulang untuk menggali lapisan makna, saya rasa itu sudah template untuk mengapresiasi karya-karya Priest manapun. Kritik kecil mencatat bahwa musiknya tidak berusaha merombak formula, tetapi nampaknya hampir semua fansnya setuju bahwa Abraxas 2 tidak sedang mengejar evolusi formal melainkan kedalaman.
Durasi 37 menit dengan 12 lagu menjaga album fokus, menghindari jebakan proyek spiritual yang cenderung melebar. Hasilnya bukan lagi opus panjang, tetapi manuskrip ringkas: padat dan bernapas. Salah satu rilisan terkuatnya dalam beberapa tahun terakhir. Dalam peta hip hop 2025, Abraxas 2 berdiri sebagai pengingat bahwa rap masih bisa menjadi kendaraan metafisik; bukan escape, tetapi excavasi. Killah Priest tidak menawarkan jawaban. Ia mempersilakan pendengar berjalan bersamanya dan, seperti biasa, sisanya adalah urusan kita dengan peta batin sendiri.
Apollo Brown – Elevator Music
Selama lebih dari satu dekade, Apollo Brown membangun reputasi sebagai salah satu produser paling konsisten dalam hip hop modern: arsitek boombap soulful yang memadukan kepekaan gospel, kesunyian Detroit, dan estetika crate-digging yang telaten. Dari Clouds hingga kolaborasinya bersama Guilty Simpson, Skyzoo, hingga para legenda seperti Ras Kass dan OC, Brown dikenal bukan hanya karena beat yang indah, tetapi karena kemampuannya memberi napas bagi MC untuk terdengar lebih dalam, lebih tajam, lebih manusiawi, bahkan untuk rapper yang terkenal dingin dan bengis seperti Planet Asia dan Joel Ortiz. Ia adalah produser yang membuat rapper terdengar seperti mereka sedang berbicara dari dada, bukan dari tenggorokan. Elevator Music menempatkan legacy itu dalam konteks instrumental penuh: tanpa vokal, tanpa narasi verbal, namun tetap identik dengan suaranya.
Dirilis pada 2025, Elevator Music menawarkan 15 trek yang membentuk lanskap emosional yang rapat namun tidak berlebihan. Judulnya sengaja bermain ironi: jika “elevator music” secara historis dipandang sebagai musik latar yang netral yang bis akita abaikan jika ada di lounge atau di dalam lift, Apollo menjadikannya sebaliknya; beat yang menuntut perhatian melalui detail, repetisi, dan tekstur halus. Hasilnya sangat impresif, bukan ambient pasif tetapi serangkaian sketsa sonik pendek yang membawa pendengar masuk ke mood yang bergerak antara reflektif, suram, dan hangat seperti memori samar yang menetap untuk dihuni (beberapa MC akan tertarik untuk menjadikannya matras ngerap di atasnya).
Secara musikal, album ini mengandalkan metode sederhana namun efektif. Palet drum yang bersahaja, bass yang digulung pelan, loop soul dan synth lembut yang membuka ruang. Tanpa MC, beat Apollo berdiri sebagai narator; groove-nya tidak berteriak, hanya mendorong sedikit demi sedikit. Tidak ada upaya mengisi ruang dengan hook besar atau struktur dramatis untuk membiarkan ruang kosong yang berbicara. Di sinilah album menemukan karakter utamanya: Elevator Music bukan beat-tape yang memamerkan keterampilan teknis, (atau pamer hasil digging seperti Madlib) tetapi studi tentang kesabaran, tone, dan kontrol emosi.
Beberapa hiphopheads mengkritik album ini terlalu santuy dibanding puncak-puncak emosional proyek kolaboratif Brown. Terlalu linear, kurang variasi ritmik. Saya pikir justru di situ letak keistimewaannya. Setiap track terdengar seperti potongan memoar instrumental, konsisten sebagai ruang introspeksi. Kritik ini valid sejauh menyangkut ekspektasi; Elevator Music bukan Trophies tanpa vokal, melainkan Clouds yang menua sehingga terdengar lebih tenang, lebih ekonomis, dan berjarak dengan ledakan.
Di tengah lanskap rap 2025 yang dipenuhi produksi maksimalis dan hook instan, Elevator Music berdiri sebagai pengingat bahwa instrumental hip hop masih dapat menyampaikan kedalaman emosional tanpa kata. Ia ekuivalen album Pelican atau Russian Circle dalam tradisi rock. Ia berguna sebagai latar (di dalam elevator/lift), tetapi juga menolak jadi sekadar latar dengan kemampuannya memberi ruang untuk introspeksi. Untuk mereka yang ingin memahami Apollo Brown bukan hanya sebagai produser untuk MC, tetapi sebagai penyusun mood maka album ini adalah bentuk kedewasaannya.
Nas & DJ Premier – Light-Years
Tak ada album lain yang mampu membelah opini para oldheads selain album ini; ada yang mengecamnya, ada yang memujinya, dengan intensitas yang membuat perdebatan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari nilai album itu sendiri. Berminggu-minggu setelah rilis, percakapan belum mereda, dan mungkin tidak akan dalam waktu dekat.
Light-Years telah lama beredar sebagai desas-desus, rumor, bahkan obsesi. Kolaborasi penuh antara Nasir “Nas” Jones dan DJ Premier sudah hadir sejak album ke-2 Nas dirilis di 1996, namun pertama kali disebut pada 2006 dalam Scratch Magazine, lalu terus muncul sebagai mitos kecil yang membayangi kultur hip hop. Ketika akhirnya tiba pada 12 Desember 2025 sebagai penutup seri Legend Has It… dari Mass Appeal Records, album ini tidak hanya menjawab penantian lama itu, ia juga memaksa kita menilai kembali apa yang masih “hidup” dari tradisi East Coast rap setelah tiga dekade.
Oke, sebelum membahas Nas yang tampil cemerlang di sepanjang album, mari letakkan dulu fondasinya: pilihan produksi DJ Premier yang menjadi sumber kontroversi album ini. Banyak yang tiba di Light-Years dengan ekspektasi sonik tertentu (termasuk saya). Mengharapkan potongan pendek sample riuh bersahutan sekelas “Represent” dan “Rockstars,” swing kinetik “Boom,” atau renyahnya drum-to-silence pada “Come Clean.” Maka tidak heran beberapa pendengar awal menilai beat-beat di album ini terdengar serba “kurang”; kurang bertenaga, kurang megah, kurang momen. Namun setelah rotasi berulang, justru terlihat bahwa Premier melakukan sesuatu yang sangat disengaja namun sering disalahpahami: voluntary constraint.
Premier menurunkan level virtuosis sampelnya/beatmaking-nya, bukan karena stok ide habis, melainkan karena ia tahu apa yang terjadi jika ia menurunkan lampu sementara Nas meningkatkan suara. Drum di sini tidak mendominasi ruang frekuensi, sampel tidak didekonstruksi menjadi serpihan, bassline bergerak sebagai jangkar naratif ketimbang ornamen. Beberapa track bahkan terasa seperti premeditated reduction: beat yang sengaja tidak mencapai titik kulminasi, seakan Premier memotong peluang untuk klimaks agar Nas menangani tekanan itu sendiri. Nada kritik bahwa beat-nya “kurang memorable” menjadi masuk akal ketika dibaca sebagai gestur anti-virtuositas, bukan kegagalan eksekusi.
“Welcome to the Underground” adalah contoh ekstrem pendekatan itu. Track ini bukan banger namun lebih menyerupai pengujian batas. Preem mengambil sample sebuah intro-rock fragment yang dibiarkan mentah, seakan melepaskan kontrol demi memberi warna grainy yang mengaktifkan peran Nas sebagai narator ruang, bukan sekadar MC. Dengan kata lain: Premier memilih ketegangan yang timbul dari jeda, repetisi, dan penolakan klimaks. Niat paling jelas nampak juga pada “Pause Tapes” yang hanya menghadirkan suara static satu detik, di-loop di atas beat renyah dengan tekstur suara vinyl. Preem sengaja menghadirkan nuansa era primitif di mana para MC membuat beat dengan cara yang sangat sederhana di kamar tidurnya memakai boombox. Track ini berhasil menemani Nas secara vivid memotret metode double-deck era pra-DAW itu.
Enam album Nas bersama Hit-Boy adalah laboratorium warna, kita bisa sepakati itu. Dan Light-Years, sebagai kebalikannya, adalah ruang gelap tempat suara menjadi cahaya tunggal. Premier menolak menjadi arsip museum; ia mengaktifkan kembali basement-studio imaginary, membatasi palet demi memaksimalkan kontur vokal Nas.
Elemen sample vokal yang dipotong-potong (vocal chops) lalu di-scratch menjadi motif repetitif sepanjang album ini, khas Preemo juga. Meskipun tidak selalu memberi kejutan, mereka menjadi elemen penting dalam upaya membuat setiap track memiliki resonansi beton New York di era lawas dan secara sengaja menempatkan Nas dalam arena ritmik yang familiar namun berjarak dari tren mainstream; memberi penekanan sebuah era di mana DJ sama pentingnya dengan MC.
Dalam perkara rima, nampaknya kita tak usah bahas soal teknis di album ini. Semua yang kalian dengar di Illmatic dapat ditemukan pula di Light-Years. Nas tak pernah kehilangan sentuhan midasnya dalam perkara itu sehingga membahas soal teknik terdengar seperti membahas teknik bernyanyi Celine Dion di albumnya. “My Life Is Real” membuka album dengan refleksi yang langsung menancap. Tracknya tidak berapi-api sebagai pembuka, namun Nas kembali menulis dengan nada seorang saksi hidup: membicarakan kematian, kemenangan kecil, kemenangan besar dan kegigihan tanpa klaim heroik. Setelah pembuka selesai, album mulai bergerak dimulai dengan “GiT Ready,” energi funk yang dibungkus keras menjadi platform bagi Nas untuk menegaskan bahwa perubahan gaya rap tidak menghapus kebutuhan dasar akan bahasa yang terkontrol dari ruang yang tak terkontrol.
Tema utama album ini selalu kembali pada satu sumbu: hari ini yang terus dibentuk oleh masa lalu dengan intensitas dan manifestasi yang berbeda di tiap lagu. Dalam “Writers” dan “Bouquet (To the Ladies),” masa lalu hadir sebagai bentuk penghormatan: kepada para bomber graffiti yang membangun lanskap visual hip hop, dan kepada para MC perempuan yang menjaga struktur emosional sekaligus intelektual kultur ini sejak awal. Sementara dalam “Junkie,” Nas menegaskan bahwa hip hop bukan sekadar profesi, melainkan dorongan fisiologis: kebiasaan motorik, afektif, dan bahkan neurologis yang tak bisa dihentikan; serupa candu. Di sini Nas mengafirmasi posisi dirinya sebagai “pecandu” rap. Sebuah garis yang kembali menghubungkannya dengan sang pelopor; Rakim dan etos “Microphone Fiend” yang ia warisi sejak muda.
Beberapa lagu terdengar lebih mengancam dari yang lain, bukan hanya dalam pilihan beat, tetapi juga dalam cara Nas menempatkan dirinya di tengah peta rap hari ini. “Madman” mengangkat momentum album di sepertiga awal dengan alur flow yang dipadatkan dan dipercepat, seolah Nas sedang memperlakukan setiap bar sebagai serangan singkat yang presisi. Di atas eerie strings yang berputar seperti sirene di kejauhan dan bass berdentum yang menekan ruang frekuensi rendah, ia menyinggung posisinya dalam industri dengan narasi singkat bahwa kedewasaan tidak menghilangkan rasa waspada atau naluri kompetitifnya. Atmosfernya gelap tanpa menjadi melodramatis, nocturnal dalam arti paling tekstural: suara yang terasa seperti berjalan sendirian di tengah kota pada jam di mana ambisi dan paranoia berbaur.
“Nasty Esco Nasir” melanjutkan ketegangan itu, tetapi beroperasi sebagai altar pengakuan diri dan penyatuan persona. Beat berbahan string masih menjadi fondasi, namun dengan kick-snare yang lebih tegas dan BPM lebih rendah memberi ruang bagi Nas untuk menampilkan identitas yang selama ini bersilangan, bertabrakan, dan kemudian berbaikan di sepanjang kariernya. Judulnya sendiri berfungsi sebagai trilogi identitas: Nasty sebagai era remaja yang haus pengakuan, Esco sebagai masa ambisi hedonistik dan kejayaan komersial, dan Nasir sebagai nama akte kelahiran yang kini ia gunakan untuk menandai fase refleksi, integritas, serta kedewasaan yang tidak lagi perlu berteriak untuk didengar. Di lagu ini, Nas tidak sekadar menautkan masa lalu ke masa kini. Ia mengunci seluruh rentang hidupnya ke dalam satu suara, menandai bahwa kontinuitas bukanlah garis lurus, tetapi proses penyatuan fragmen yang dulu terasa saling bertentangan.
Beberapa track lain berbentuk kelanjutan dari benang sejarah yang dimulai sejak Illmatic, debut mahakaryanya itu. “N.Y. State of Mind Pt. 3”, dan duetnya (kembali) bersama AZ di “My Story Your Story” yang terasa seperti percakapan antara dua sahabat yang telah melewati lingkar perjalanan panjang. Musiknya landai, menghindari kejutan, hanya latar sederhana bagi pertemuan orang dewasa yang memeriksa kembali warisan tanpa romantisasi. Di lagu-lagu tersebut Nas tidak sedang bernostalgia; ia memperpanjang garis waktu. Ia menatap New York bukan sebagai monumen, tetapi sebagai organisme: kota yang membiarkan nama graffiti hilang namun tidak benar-benar lenyap, kota yang menata ulang ruang sambil menyisakan bayangan masa lalu di setiap pojoknya. Di sini Nas berperan ganda: kurator sejarah dan warga kota, menulis bukan dari kejauhan tetapi dari dalam perubahan itu sendiri.
Album ini juga memperlihatkan kelembutan dan refleksi yang acap kali terdengar dalam katalog Nas belakangan, namun kali ini hadir lebih jelas. Sebuah nuansa yang menunjukkan apa arti menjadi tua dalam rap tanpa kehilangan ketajaman pengamatan dan energi naratifnya. Lagu seperti “Sons (Young Kings)” membuka ruang lain dalam narasi album: ia bukan sekadar polemik atau eksplorasi ritme, tetapi meditasi tentang pengasuhan, harapan generasi berikutnya, dan ruang aman yang diinginkan seorang ayah bagi anaknya. Beat-nya yang lembut, piano yang halus, dan pengucapan Nas yang lebih tenang menciptakan suasana yang intim dan tulus, di mana Nas berbicara langsung kepada putranya juga kepada generasi anak laki-laki kulit hitam pada umumnya.
“It’s Time” menegaskan sisi lain dari kedewasaan artistik Nasir Jones: pengakuan akan ambisi dan identitas yang terus berkembang tanpa mengabaikan pengalaman masa lalu maupun realitas pertambahan usia. Beat yang memuat potongan-potongan Steve Miller Band, diolah oleh DJ Premier dalam tekstur boom-bap yang halus namun berlapis, memberi dasar bagi Nas untuk menggambarkan perjalanan hidupnya sebagai sesuatu yang bukan retrospeksi semata, tetapi juga kesiapan untuk bab berikutnya. Tema waktu, evaluasi diri, dan tekad untuk terus berdiri kuat menjadi poros liriknya. Nas menunjukkan bahwa kedewasaan bukan berarti mundur dari ambisi, hanya saja sekarang ia lakukan dengan sadar dan terhitung.
Di kedua lagu yang terakhir disebutkan tidak ada perasaan pertarungan melawan waktu yang biasa muncul ketika seniman memasuki fase matang kariernya. Sebaliknya, Nas mengeksekusinya dengan gemilang sebagai penerimaan kritis dan reflektif:
Penutup Light-Years, “3rd Childhood,” berdiri sebagai monumen tematik yang menghubungkan album ini dengan sejarah panjang karier Nas. Judulnya secara eksplisit merujuk pada “2nd Childhood,” lagu dari Stillmatic (1999), yang dulu menjadi refleksi tentang orang-orang dewasa yang tetap terjebak dalam pola perilaku dan identitas yang tidak berkembang. Dengan menamai lagu penutup ini sebagai “3rd Childhood,” Nas bukan sekadar memanggil kembali referensi katalognya sendiri, tetapi menandai bab baru dalam narasi hidup dan rapnya, tanpa perlu melakukan pembuktian apapun.
Lagipula, apa lagi yang harus Nas buktikan? dalam waktu 5 tahun terakhir saja ia melahirkan enam album dalam dua trilogi (King’s Disease dan Magic) dengan kualitas prima, membidani Mass Appeal sebagai label rekaman yang merilis album-album hip hop prominen sejak 2014, dari album J Dilla hingga Dave East, album Boldy James hingga Run The Jewels. Nas pun memperkuat fondasi sejarah hip-hop melalui kontribusi finansial dan advokasi untuk The Hip Hop Museum di Bronx yang sempat tersendat pembangunannya, agar dapat kembali bergerak dan membuka ruang arsip bagi generasi mendatang.
Apa pun perbedaan penilaian yang hadir, Light-Years berdiri sebagai karya yang menghormati sejarah tanpa menguburkannya, sebagai pernyataan craft yang matang dari dua master yang memahami bahwa hip hop adalah medan hidup yang bergerak bersama waktu. Perbedaan penilaian terhadap Light-Years justru menegaskan posisi album ini yang memberi tempat terhormat bagi sejarah tanpa mengawetkannya, menawarkan model bagaimana tradisi tetap hidup ketika dikelola dengan jarak, bukan dengan (melulu) nostalgia. Light-Years tidak mencoba memutar kembali waktu, sebaliknya ia membuka ruang percakapan antara masa lalu dan masa sekarang, antara kota dan suara, antara arsip dan pengalaman.
Dalam konteks daftar album hip hop terbaik tahun ini, Light-Years, sekali lagi, tidak hanya memberi tribut kepada akar East Coast rap, tetapi juga menunjukkan bahwa, bahkan setelah begitu banyak tahun, suara hip hop yang autentik masih memiliki tempat untuk berbicara dengan tegas—tanpa perlu bersikap retro; cukup menjadi diri sendiri. Dan mungkin inilah keistimewaannya: tidak ada kesan album ini dibuat demi memanen simpati sejarah. Light-Years terasa seperti pengingat bahwa tradisi bukan beban, melainkan energi yang menunggu cara baru untuk bersinar.
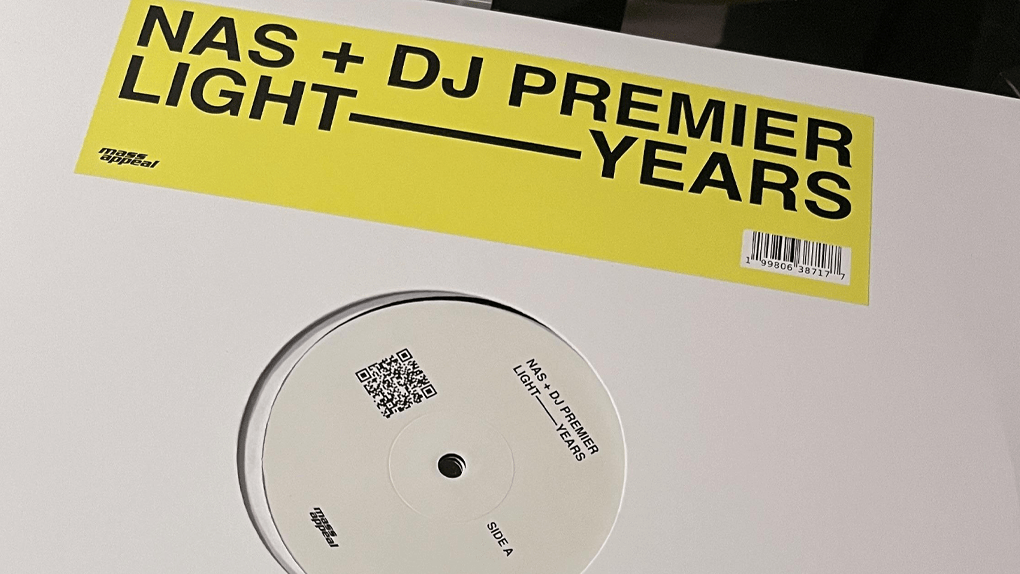
Leave a comment